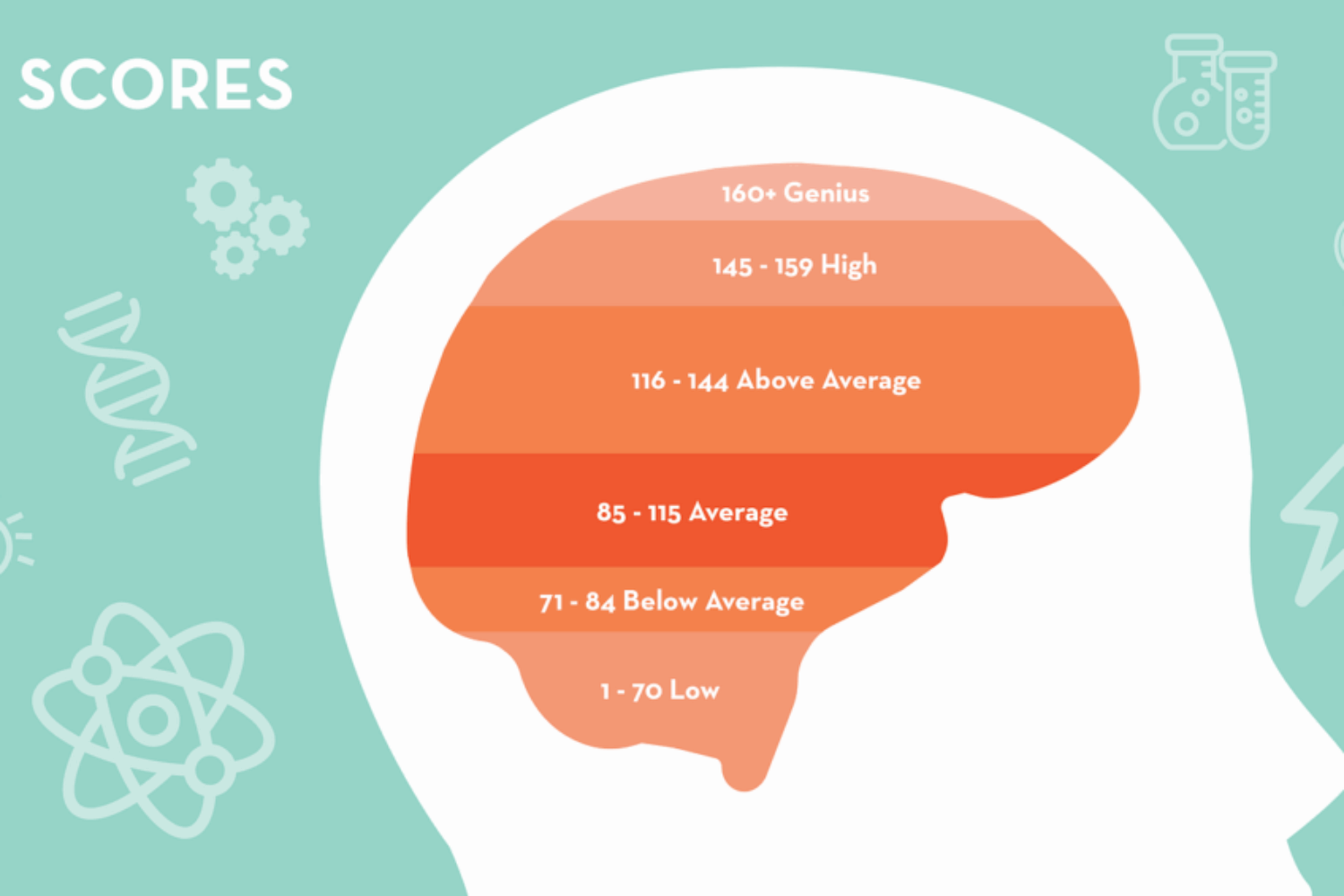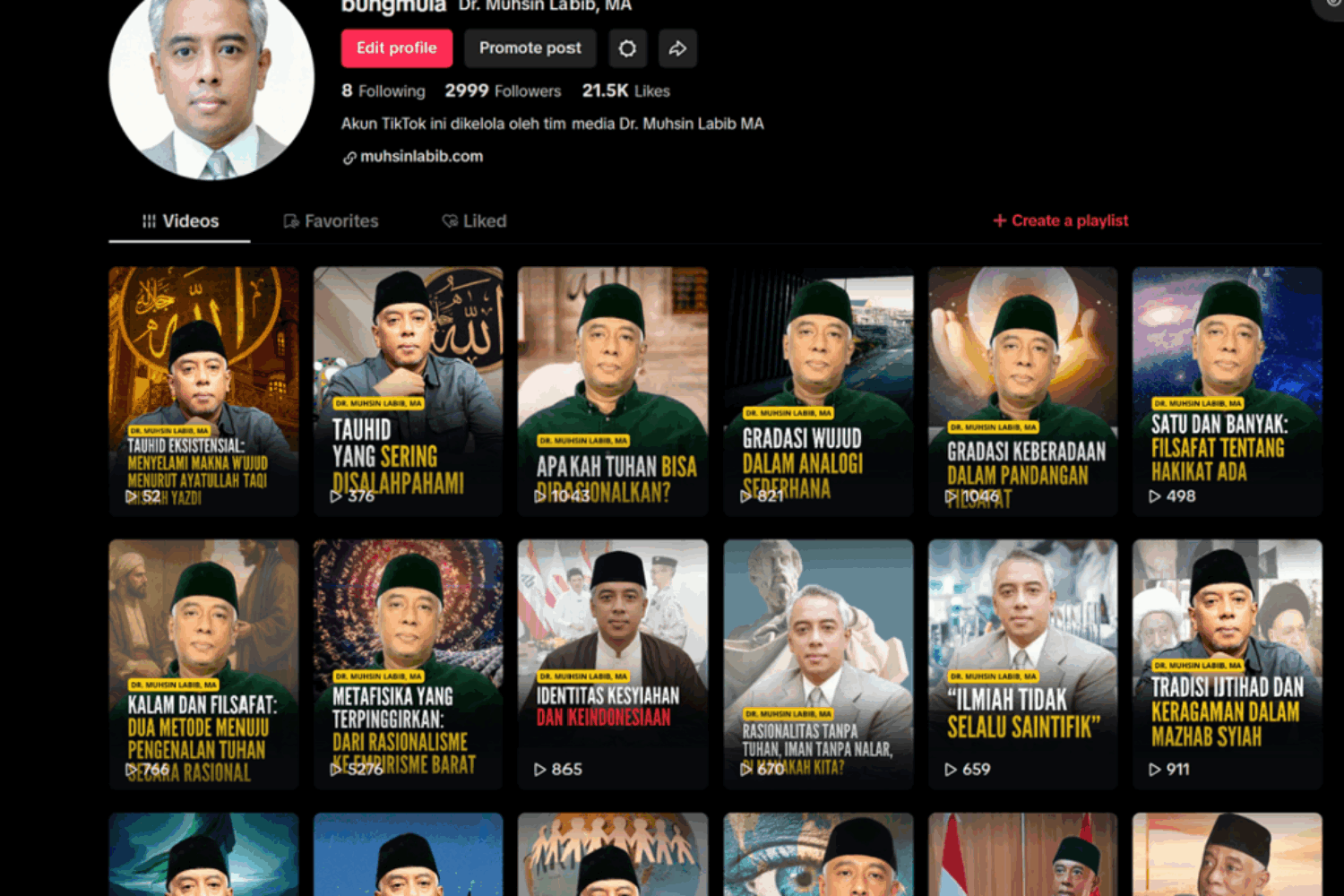Kegaduhan penggantian nama Rumah Sakit Umum “Al-Ihsan” menjadi “Welas Asih” telah membesar menjadi skandal nasional. Keputusan seorang penguasa provinsi, yang kerap mengibarkan identitas lokal sebagai kearifan lokal atau panji keaslian, memicu badai kontroversi. Sejumlah agamawan mengecamnya sebagai penghinaan terhadap Islam, menganggap “Ihsan” sebagai pilar suci trilogi akidah: Iman, Islam, Ihsan. Masyarakat pun terpecah—pro dan kontra—dalam pertarungan yang jauh melampaui soal nama. Ini adalah jendela menuju fenomena kelam: nativisme selektif yang bersemayam di balik jubah pelestarian budaya. Dengan semangat yang mencurigakan, gerakan ini menarget simbol-simbol yang tidak dianggap sebagai lokal alias bernuansa Arab yang sebagian merupakan terma Islam—dari institusi hingga nama pribadi. Namun, ironisnya, gelombang nama Barat seperti Fredi, Natasha, atau Jonathan, yang membanjiri akta kelahiran generasi milenial dan Gen-Z menurut catatan Dukcapil, luput dari sorotan. Klaim “keaslian” ini, ketika ditelusuri, ambruk di hadapan kontradiksi linguistik dan sejarah yang mencolok.
Nativisme yang riuh ini memperlihatkan wajah paradoksal. Nama seperti Muhammad, yang telah berurat-akar di Nusantara selama tujuh abad—dari era Walisongo, kolonialisme, hingga republik—dituduh sebagai pendatang yang menggerus identitas lokal. Sebaliknya, nama seperti Kevin atau Chelsea, yang asing secara etimologis dan kultural, diterima sebagai lambang modernitas tanpa cela. Standar ganda ini bukan kebetulan, melainkan bias politik yang terselubung. Bahasa itu sendiri menelanjangi kepalsuan klaim “anti-asing”: kata “asli” berakar dari Arab aṣl (أَصْلٌ), “palsu” dari bāṭil (باطل), bahkan “umum” dalam “Rumah Sakit Umum” berasal dari ‘āmm (عام). Bahasa Sunda, yang diagungkan sebagai simbol kemurnian, menyimpan warisan Arab seperti “kitab” dan “adab”, serta Sanskerta seperti “darma”. Logika nativisme runtuh ketika alat ukurnya sendiri adalah produk akulturasi berabad-abad.
Klaim keaslian berbasis suku atau daerah justru melemahkan Indonesia sebagai bangsa modern. Negara ini lahir dari kesepakatan lintas budaya, bukan dominasi satu kelompok. Warga negara asli adalah mereka yang memegang NIK, bangga berbahasa Indonesia, dan menjadikan Pancasila serta UUD 1945 sebagai pegangan hidup—tanpa harus mengorbankan identitas kesukuan atau keyakinan. Polemik nama rumah sakit ini mengabaikan hakikat kata sebagai abstraksi manusia. “Al-Ihsan” dan “Welas Asih” hanyalah dua label untuk esensi yang sama: kebaikan. Menolak “Al-Ihsan” dengan alasan “keasingan” adalah keliru. Segala yang telah menyatu dalam nadi masyarakat melalui akulturasi—entah Arab, Sanskerta, atau Eropa—adalah lokal. Menafikan budaya dan bahasa lokal dengan alasan agama adalah reduksi terhadap Islam. Tapi menolak budaya dan bahasa luar yang telah menjadi bagian dari proses akulturasi berabad-abad adalah reduksi terhadap nasionalisme dan kearifan lokal. Welas Asih bukan antitesis Al-Ihsan; keduanya islami, keduanya Nusantara. Jika mencari padanan yang lebih “autentik”, kata “darma” atau “derma” (warisan Sanskerta) justru lebih mencerminkan akar budaya Nusantara.
Bagi banyak orang, drama penggantian nama ini mubazir, bahkan menggelikan. Pergantian nama tak signifikan kecuali untuk memicu dikotomi palsu: Islam sebagai “asing” versus budaya lokal sebagai “asli”. Di Jawa Barat, nama seperti “Muhammad Ujang” atau “Fatimah Nani” adalah mozaik sintesis kultural, bukan pengkhianatan budaya. Sebaliknya, tren nama Barat yang merajalela mencerminkan globalisasi tak tersaring, namun luput dari kritik. Paradoksnya mencolok: nama Arab yang telah terlokalisasi dan menjadi bagian organik identitas Muslim Indonesia dianggap ancaman, sementara nama Barat yang diadopsi tanpa kedalaman kultural diterima begitu saja. Menyangkal kontribusi budaya Arab dalam bahasa Indonesia sama dengan menolak eksistensi bangsa ini, yang berdiri di atas bahasa pemersatu.
Pertikaian ini mereduksi Islam sebagai agama universal yang lentur beradaptasi dengan lokalitas, sekaligus mengabaikan fakta bahwa akidah tak bergantung pada kosakata.
Tuduhan bahwa “Welas Asih” menghina akidah juga berlebihan. Dalam konteks Jawa, “Welas Asih” justru mencerminkan nilai keislaman yang telah terinkulturasi. Argumen perlindungan trilogi akidah kehilangan pijakan ketika disandarkan pada nama, karena Islam dan Arab bukanlah entitas yang identik. Bayangkan skenario sebaliknya: jika “Welas Asih” diganti menjadi “Al-Ihsan”, akankah protes serupa bergema? Kemungkinan besar tidak, mengungkap bias yang mendasari polemik ini.
Polemik ini, pada hakikatnya, adalah pengalihan energi bangsa dari isu yang lebih mendesak. Rumah sakit harusnya memperjuangkan pelayanan yang manusiawi, adil, dan bermutu—bukan plang nama. Identitas seseorang tidak ditentukan oleh apakah ia bernama Ferdi, Deddy, atau Ujang, melainkan oleh integritas dan kontribusinya. Kohesi sosial terkikis ketika nama Muhammad dipersoalkan, tetapi Jonathan dibiarkan biasa. Nama adalah kanvas sejarah, bukan benteng identitas. Ketika seorang koruptor bernama “Surya” merampok rakyat, atau RS “Welas Asih” gagal memberikan welas asih, nama hanyalah kosmetik yang menipu.
Dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, keragaman nama—Arab, Sanskerta, Barat, maupun lokal—adalah arsip hidup perjumpaan peradaban. Yang patut diperjuangkan bukan kemurnian label, melainkan konsistensi membangun negeri berdasarkan Pancasila dan keadilan sosial. Seperti kata Pramoedya Ananta Toer: “Jangan pandang bahasanya, tapi isinya.” Martabat bangsa tidak ditentukan oleh bunyi kata, melainkan makna perbuatan di baliknya. Sejarah tak mencatat nama kita, melainkan jejak yang kita ukir di kanvas zaman.