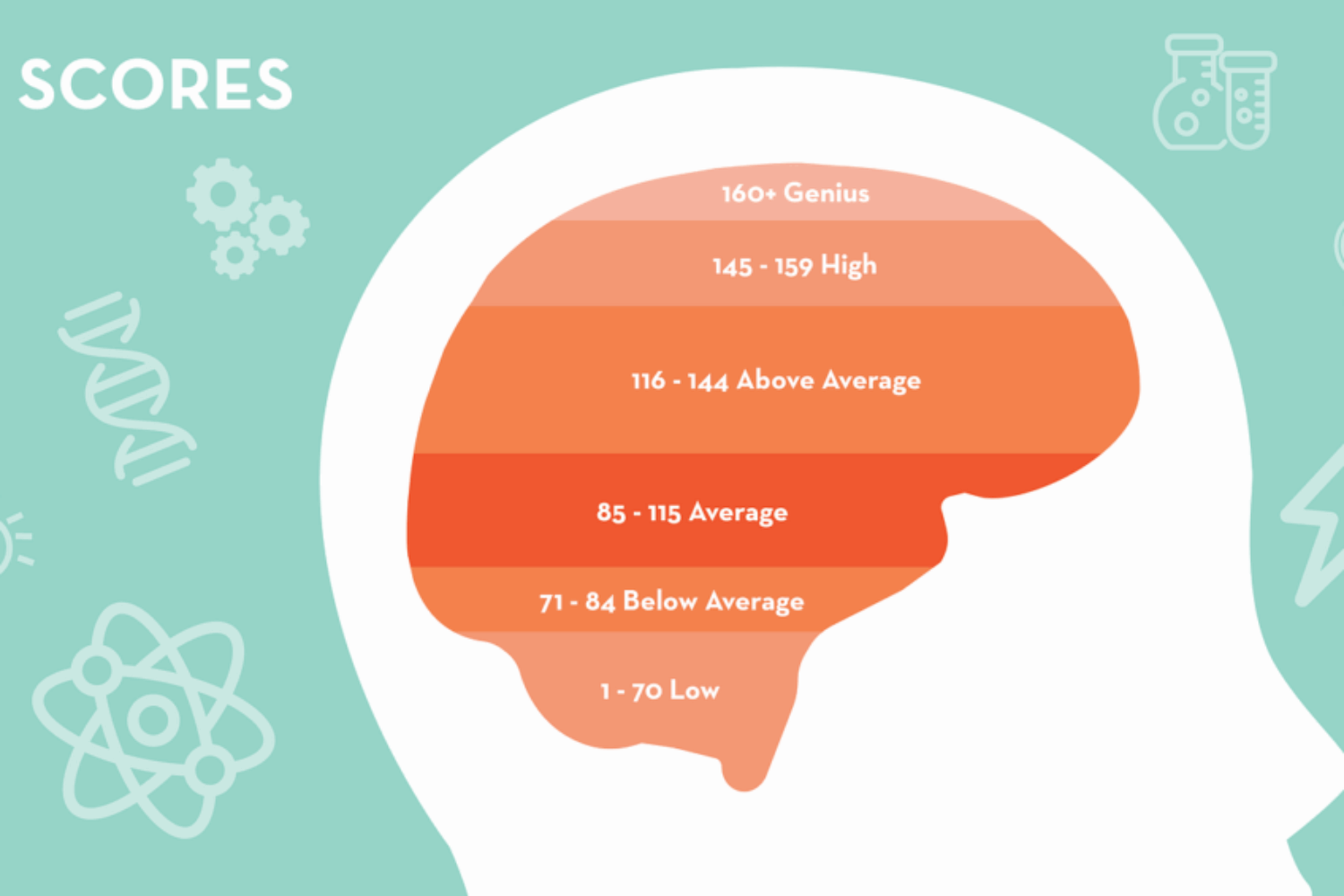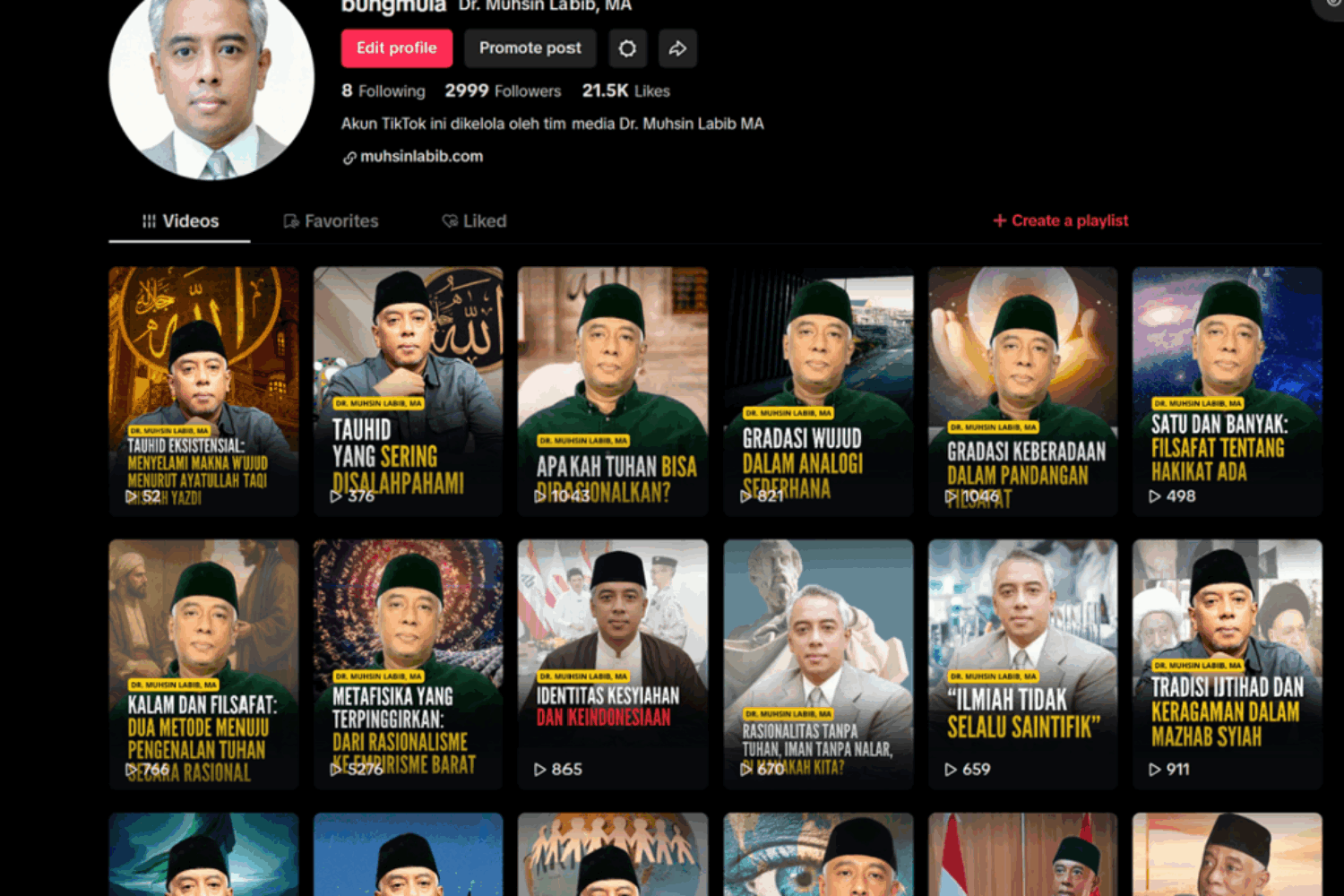Pesta perburuan telah usai. Sahara Karbala yang ganas kini dirajut benang-benang kesunyian, lebih kejam dari terik matahari. Kafilah syahadah agung telah dibantai di dataran Nainawa yang memerah darah. Hentakan kaki kuda sang penjarah telah sirna, meninggalkan debu yang perlahan turun, bagai tirai kelam menutup pentas Ghadiriyah yang sakral. Yang tersisa hanya gema: jerit ratap Zainab binti Ali bersama saudari-saudarinya, suara yang menyayat, membumbung, merobek selaput angkasa kelabu, memohon keadilan kepada Yang Maha Mendengar.
Sorban putih al-Husain, lambang kemuliaan keturunan Nabi, terlempar, diinjak-injak kehinaan. Jubah perang Abu Abdillah yang gagah telah dirampas, diperlakukan bagai rampasan perang najis. Pedang Dzulfiqar, warisan Sang Singa Allah, terpelanting, cahayanya padam. Jasad Imam al-Husain, cucunda kesayangan Rasulullah, terkoyak tak berbentuk, diinjak kuku-kuku kuda haus darah. Ali Akbar, pemuda penuh harapan, terbujur kaku. Al-Abbas, pembawa panji dan penawar dahaga, terkapar tanpa lengan, dikhianati sungai yang ia datangi. Al-Hurr yang bertaubat, terkoyak hutan tombak musuh. Bayi Ali Asghar, putra bungsu al-Husain, pucat pasi oleh debu dan dahaga yang tak terobati. Pesta perburuan iblis itu usai, menyisakan kesunyian mengerikan bagai kain kafan raksasa yang menyelimuti Nainawa.
Yang terdengar kini hanya senandung lirih Sukainah, bocah kecil yang tertunduk, nyanyian duka menggantikan tangis. Hembusan napas pendek Atikah tercekat, menahan penderitaan tak terucap. Yang terlihat hanya wajah-wajah kusut para bidadari surga yang turun ke bumi, menyimpan samudera derita di balik sorot mata redup. Di tengah hamparan syuhada suci, jasad al-Husain terbujur sendiri, tersayat-sayat, tanpa kepala, di atas pasir yang haus. Di Karbala hari itu, kebenaran itu sendiri telah dipancung. Kebenaran yang tak dimandikan, tak dikafani, tak dikebumikan dengan hormat, tak disalati oleh umat yang mengaku mencintai kakeknya. Sungguh, umat Muhammad telah membunuh “Muhammad” yang kedua.
Malam pekat menelan sisa cahaya Karbala. Zainab, Singa Betina Bani Hasyim, bersama saudari-saudarinya dan kemenakannya yang selamat, berkumpul di bawah langit terbuka. Kemah-kemah perlindungan mereka telah hangus, menyisakan abu dan kepedihan. Berkat ketajaman lidah Zainab, menantang Umar bin Sa‘d dengan hujjah setajam pedang, rombongan ratu-ratu duka itu untuk sementara terhindar dari gangguan lebih lanjut. Di pundak Zainab kini bergantung masa depan keluarga al-Husain, nasib anak-anak yatim, dan pesan Karbala yang harus disampaikan ke dunia. Dialah Ratu Karbala, benteng terakhir kehormatan Nabi.
Jingga pagi yang kejam menyapu dataran Ghadiriyah, menyinari kehancuran. Pasir angin gurun berdesir, seakan menampar wajah pasukan berkuda Ibnu Ziyad yang bersiap mengakhiri tugas biadab mereka. Zainab membisu, matanya memancarkan keteguhan baja. Sukainah berdiri terpaku, kecil dan rentan di tengah puing-puing tragedi. Atikah tampak lesu, tenaganya terkuras. Ali Zainal Abidin, sang Imam yang sakit, menatap dengan mata berkaca-kaca jasad keluarga dan sahabatnya yang tergeletak tak terurus, disucikan darah mereka sendiri.
Detik-detik perpisahan yang menghancurkan pun tiba. Gemerincing besi mengiris kesunyian. Tali-tali rantai dingin mengikat pergelangan tangan dan kaki para ratu suci, yang tetap setia mengenakan busana hitam—lambang duka abadi. Kepala Abu Abdillah, Sang Cahaya, bersama kepala para pendukung setianya, dipungut dari tanah, dibersihkan seadanya dari darah dan debu, lalu ditancapkan dengan keji di ujung tombak. Kepala-kepala syuhada itu menjadi tontonan nista, piala kemenangan para penjahat.
Perintah berbaris bergema, suaranya kasar, mengoyak kesakralan pagi. Derap kaki kuda yang angkuh menggantikan desiran angin. Kaki-kaki mungil Sukainah dan para wanita, melepuh oleh perjalanan dan air mata, dipaksa melangkah menuju ketidakpastian yang kelam.
Zainab, Sang Dewi Sahara yang perkasa, menyiapkan diri. Ia akan memperagakan kesyahidan jiwa, keteguhan, dan kehormatan di atas pentas pasir кемuning yang luas. Babak ketiga tragedi prahara dimulai: “Pawai Dewi-Dewi Hitam Sahara” akan dipersembahkan kepada sejarah, mengguncang singgasana para tiran.
Raungan tangis putri-putri Nabi menyayat sukma, merobek hati siapa pun yang masih memiliki nurani. “Geraaak!” teriak putra sahabat Sa‘d bin Abi Waqqash, suaranya menggelegar, menggetarkan pasukan yang mulai bergerak.
Zainab menoleh untuk terakhir kalinya ke jasad tak berkepala adiknya. Suaranya, parau namun penuh tekad, berbisik ke angin Karbala: “Maafkan kami, wahai Cahaya Mataku! Kami tak berdaya! Mereka tak izinkan kami memandikanmu, mengafanimu, mengebumikanmu dengan layak! Selamat berpisah, Abangku! Selamat tinggal, Ayahku! Selamat tinggal, Pemimpinku! Demi Allah, anak-anakmu yang yatim akan kujaga, kehormatan keluargamu akan kuperjuangkan hingga tetes darah terakhirku! Pesanmu akan kusebarkan, walau langit runtuh menimpaku!”
Pasukan Ibnu Sa‘d bergerak, meninggalkan Karbala yang berdarah. Kuda-kuda melangkah, roda kereta tawanan berderit. Jasad para syuhada, masih terbujur di tanah terbuka, tampak semakin kecil di kejauhan, bagai titik-titik hitam di hamparan pasir. Semakin mengecil, hingga lenyap ditelan cakrawala buram. Yang tertinggal hanya padang sunyi, debu yang menutupi darah, dan nyanyian abadi angin gurun yang meratapi.