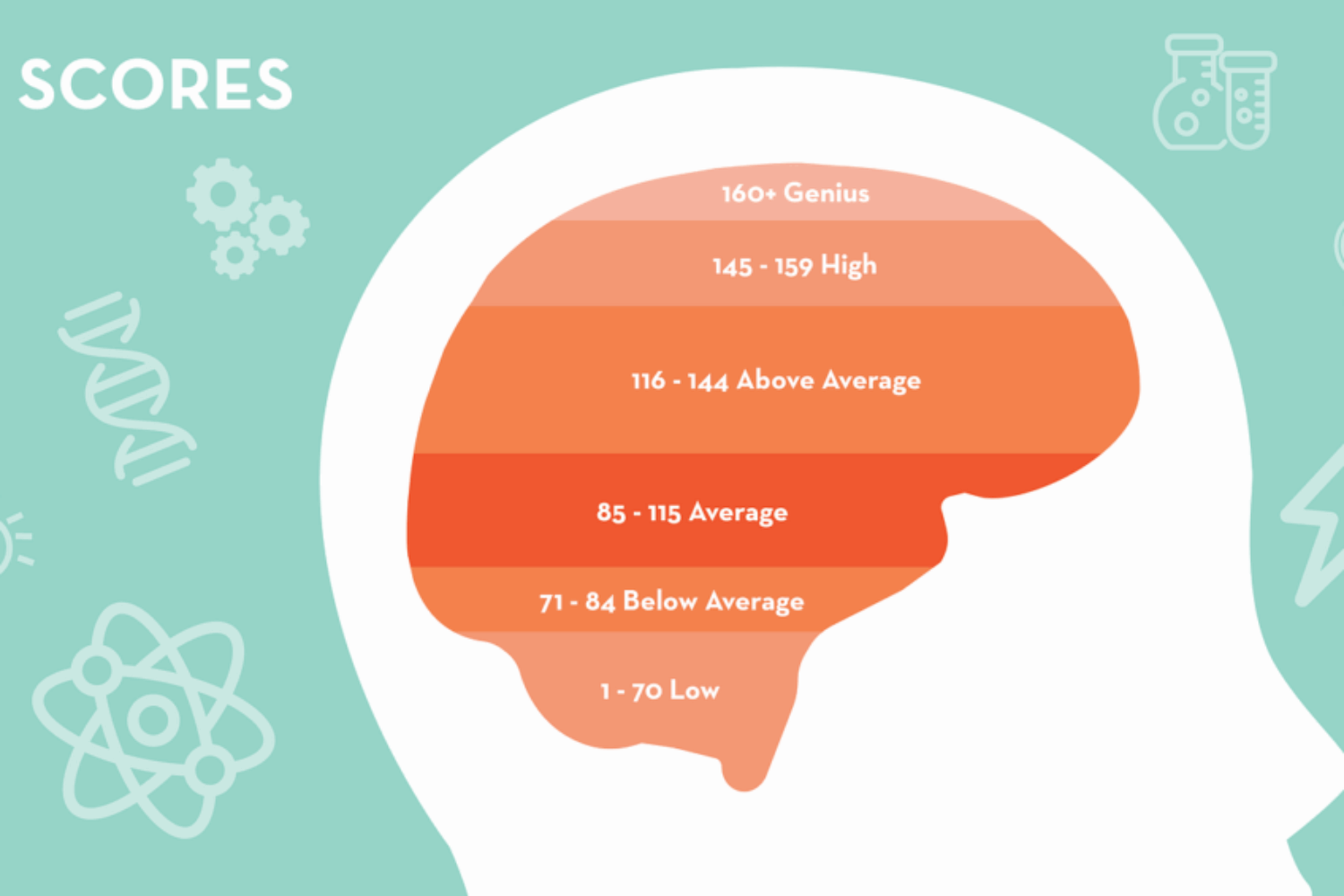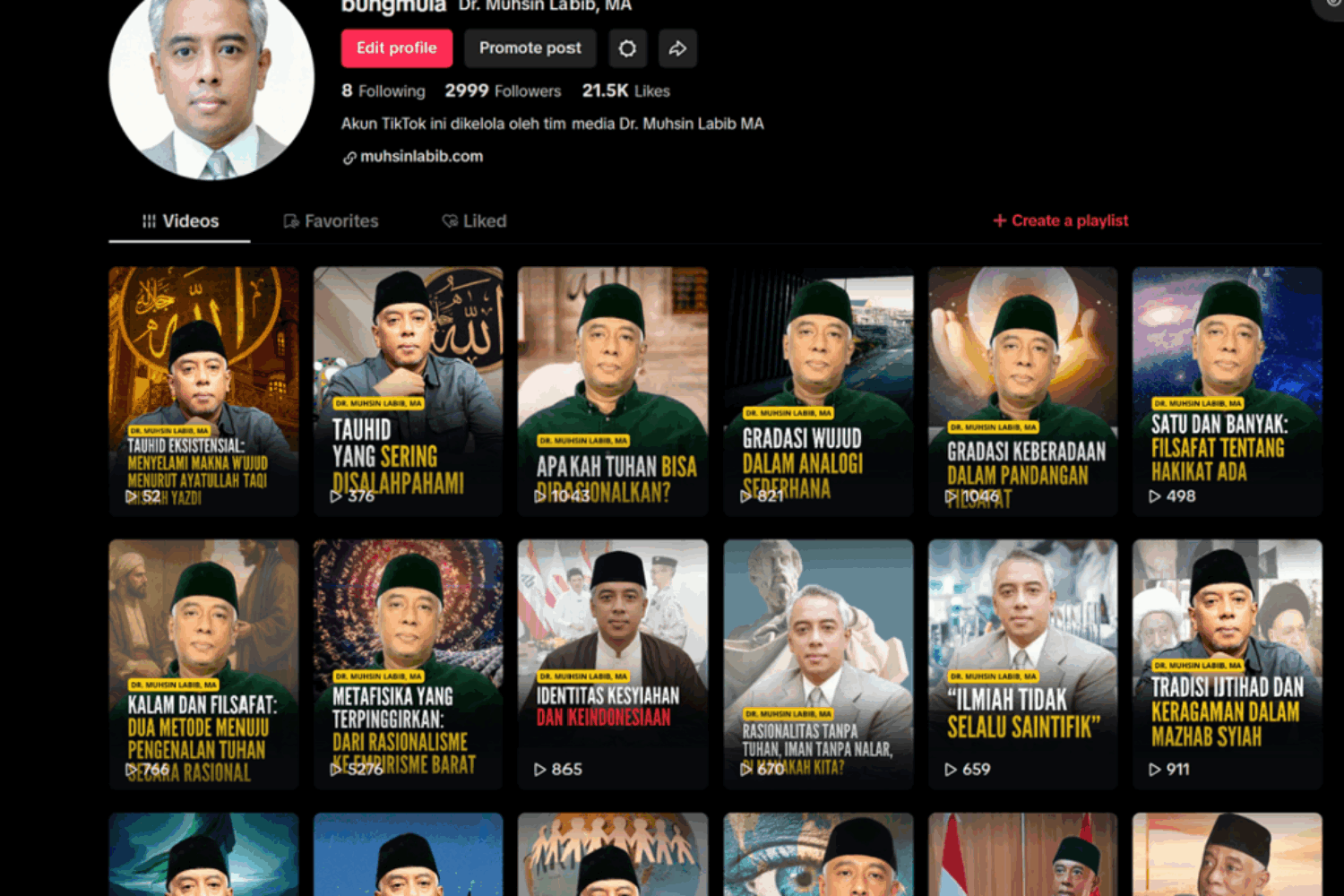Langit sepuluh Muharam di ambang petang, bagaikan lelehan tembaga yang membeku, merah kelam menyaksikan luka umat. Di hamparan gurun Nainawa yang gersang, debu menari dalam angin kering, seakan meratap akan tragedi yang akan terukir abadi. Di jantung tanah yang haus itu, terbentang panggung kelam kemanusiaan: umat yang bersumpah atas nama Muhammad, justru menghunus pedang pembunuh ke arah cucu Muhammad yang suci.
Drama Karbala memasuki babak paling nestapa, di mana nafsu kuasa yang buta menggantung nurani dan menginjak-injak kemanusiaan.
Syimr bin Dzil-Jausyan, iblis bertulang, menjelma tiran di panggung kekejian. Pedangnya bukan menari dengan keanggunan, melainkan meraung dengan kebuasan yang memilukan. Setiap sabetan adalah nyanyian kematian, merobek jasad Al-Husain, putra Fatimah Az-Zahra, permata Rasulullah. Daging suci itu terkelupas, tulang mulia itu terpapar. Dari bibir Sang Syahid yang tersiksa, meluncur jeritan parau yang menusuk relung langit: “Wa Muhammadah! Wa Aliyah! Wa Hasanah! Wa Ja‘farah! Wa Hamzatah! Wa Aqilah! Wa Abbasah! Wa Qatilah!” Setiap nama yang disebut adalah cakrawala cinta yang menjauh, setiap luka yang ditoreh adalah pengkhianatan yang menderu.
Tubuh itu, mahakarya kesabaran dan keteguhan, kini bagai kanvas yang dilumuri darah dan daging tercabik. Tak sejengkal pun anggota yang selamat dari amuk pedang yang haus. Lalu, tibalah saat yang menghentikan nafas waktu. Syimr mengarahkan mata pedangnya, dingin dan kejam, ke leher Sang Cahaya. Di bawah tatapan langit yang murung, algojo itu menggerakkan kepala cucunda kesayangan Nabi itu ke kanan dan ke kiri—penghinaan terakhir sebelum pemisahan abadi. Pedang itu membelah dengan tenang yang mengerikan, memutus nyawa dari jasad yang suci.
Gema tangis membumbung, menerobos awan. Jeritan wanita-wanita suci Ahlulbait, putri-putri Nabi, adalah ratapan kosmis yang mengoyak tirai langit. Mereka menyaksikan tubuh Al-Husain menggelepar dalam tarian maut terakhir di atas tanah Karbala yang sakral, sebelum akhirnya diam, terkapar dalam kemuliaan syahid yang tak terbantahkan.
Namun, nafsu kebinatangan belum puas. Sebelum darah suci itu kering, serigala-serigala berjubah manusia menyerbu. Ju’urah bin Hauyah merampas jubah Sang Imam. Panah dan busur pusaka diperebutkan dengan rakus oleh ar-Rahil bin Khaitsamah, Al-Ja’fi bin Syabib al-Hadhrami, dan Jarir bin Mas’ud al-Hadhrami—bagaikan burung nasar yang memakan bangkai. Ishaq bin Hauyah melucuti pakaian dari jasad tak berdaya. Al-Akhnas bin Mirtsad mencabut sorban kebanggaan. Al-Aswad bin Khalid merampas sepasang sepatu sederhana. Dan Jadal, dalam kebodohan dan keserakahan yang tak tertahankan, memotong jari Al-Husain hanya untuk merampas cincin—simbol kesederhanaan Sang Pemimpin Para Pemuda Surga.
“Pesta Iblis” mencapai puncaknya. Untuk menyempurnakan kejahatan Yazid dan pasukannya yang durjana, jasad Al-Husain yang tak bernyawa diinjak-injak, diterjang, dan dibanting oleh sepuluh kuda yang dikendalikan dengan sadis. Sementara debu kehormatan Nabi diterbangkan oleh kuku-kuku kuda, di seberang kemah musuh, Umar bin Sa’ad dan bala tentaranya menenggak khamar, bersulang atas “kemenangan” mereka dalam pesta pora kebiadaban.
Di kemah duka Ahlulbait, takbir bergaung lirih, bercampur jerit kepedihan yang menyayat. Tatkala kuda jantan putih kesayangan Sang Imam berlari kencang tanpa penunggang, membawa kabar nestapa tanpa kata, seluruh isi kemah tersentak. Zainab Al-Kubra, singa betina yang tabah, bersama wanita-wanita suci keluarga Nabi, berhamburan memeluk kuda penuh luka itu. Suara mereka parau, pecah oleh duka yang tak tertanggungkan: “Wa Husainah! Wa Qatilah! Wa Akbah!” Seruan itu adalah ratapan bumi dan langit, pengakuan atas kepergian Sang Cahaya yang dibunuh dengan keji.
Dan Al-Husain pun terbang. Terbang meninggalkan jasad yang terkoyak, menuju pangkuan Kekasih Yang Maha Tinggi. Seulas senyum terukir di wajahnya—senyum kemenangan abadi atas kebatilan. Dunia bergetar menyambut kepergiannya.
Merpati-merpati di emperan masjid Madinah dan halaman Ka‘bah terbang ketakutan, seakan ikut meratap duka maha besar. Tanah dalam botol di bilik Ummu Salamah, yang diberkahi Nabi, berubah menjadi darah segar—tangisan bumi atas anaknya yang suci. Langit bergemuruh murka, awan gulita bergulung menutupi matahari, bagaikan kain kafan raksasa untuk Sang Syahid Agung. Bunga-bunga tulip gugur, menangis darah di padang rumput. Para pujangga tergagap, kata-kata mengering di kerongkongan. Malaikat terhenyak, tak percaya menyaksikan pembantaian keji sekelompok manusia durjana atas cucu Nabi, buah cinta Fatimah Az-Zahra, penghulu wanita surga.
Di Nainawa, pada petang kesepuluh Muharam, kemanusiaan terbang ke pangkuan Yang Ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un—Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nya kami kembali.
Merpati kepakkan sayap luka,
Terbang taburkan sejuta cinta.
Menggelepar, relakan raga dan darah.
Selamat tinggal, gadis-gadis yatim Muhammad!
Selamat tinggal, jasad-jasad memerah tak terurus!
Selamat tinggal, kesetiaan teguh dan pengkhianatan hina!
Dan kalian, penenggak darah kesyahidan!Selamat “meringis”, pedagang firman!
Selamat atas kemenangan semu,Penjaja sabda, penganjur “perdamaian” palsu,
Penghuni mihrab gemerlap namun hampa,
Tokoh berbusana rapi kebohongan,
oara “rekant” sok suci di Madinah dan Mekah,
gerombolan saksi dusta,
tuan tanah kikir, juragan kurma rakus,
pemilik gudang riwayat palsu,
kakon rekayasa, khatib titipan,
agamawan abal-abal penyembah tahta di Kufah dan Syam!
Pesta kalian di dunia, nestapa abadi di akhirat menanti.
Karbala takkan lupa. Sejarah takkan diaa hingga akhir zaman. Umat Muhammad telah membunuh “Muhammad”…