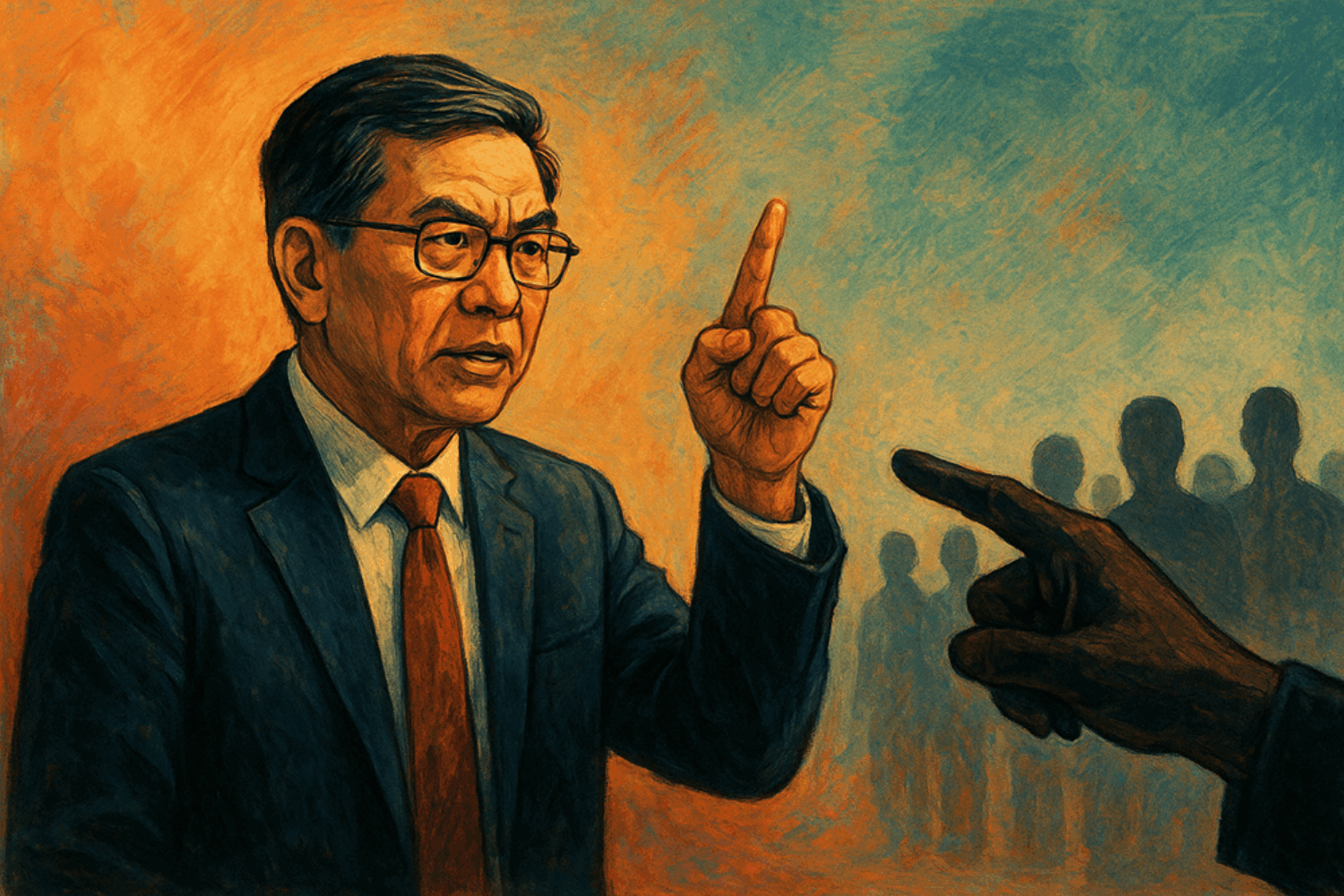Nasionalisme kosmetik merujuk pada ekspresi kebanggaan dan cinta terhadap tanah air yang bersifat dangkal, seremonial, dan lebih menonjolkan simbol ketimbang substansi. Fenomena ini mencerminkan kecenderungan untuk menampilkan rasa nasionalisme melalui gestur-gestur lahiriah—seperti mengenakan atribut nasional atau mengunggah konten bertema kebangsaan di media sosial—tanpa diimbangi oleh tindakan nyata yang mencerminkan komitmen mendalam terhadap kemajuan bangsa. Kita akan menelusuri ciri-ciri, dampak, serta perbedaan nasionalisme kosmetik dengan nasionalisme sejati, sambil mempertimbangkan bagaimana fenomena ini membentuk wajah identitas nasional di era modern.
Nasionalisme kosmetik memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari bentuk nasionalisme yang lebih mendalam. Ia kerap terwujud dalam kegemaran akan simbol dan ritual. Pada momen-momen seperti Hari Kemerdekaan, masyarakat sering mengenakan pakaian batik, memasang pin Garuda Pancasila, atau mengibarkan bendera merah-putih. Upacara bendera dan nyanyian lagu kebangsaan menjadi ajang ekspresi nasionalisme yang antusias, namun sering kali berhenti pada tataran seremonial tanpa makna yang lebih dalam. Selain itu, nasionalisme kosmetik ditandai oleh minimnya aksi nyata. Mereka yang menganutnya cenderung tidak terlibat dalam isu-isu substansial seperti ketimpangan sosial, korupsi, atau pengelolaan lingkungan. Kritik terhadap kebijakan pemerintah mungkin dilontarkan di media sosial, namun jarang diikuti oleh tindakan konkret seperti menjadi relawan, mengadvokasi keadilan, atau berpartisipasi dalam proses demokrasi seperti pemilihan umum.
Fenomena ini juga bersifat emosional dan instan. Rasa bangga terhadap tanah air kerap meletup secara spontan—misalnya, saat tim olahraga nasional bertanding atau ketika seorang warga negara meraih prestasi internasional—namun emosi ini cepat mereda begitu peristiwa berlalu. Kehadiran media sosial memperkuat apa yang bisa disebut sebagai “nasionalisme digital.” Mengganti foto profil dengan bendera nasional, memposting konten bertema kebangsaan, atau menggunakan tagar viral menjadi cara seseorang dianggap nasionalis, meski tanpa memahami konteks atau berkontribusi secara nyata.
Lebih jauh, nasionalisme kosmetik kadang-kadang menjadi kedok bagi rasisme implisit dan ujaran kebencian. Di balik semangat kebangsaan yang ditampilkan, sejumlah individu atau kelompok mungkin menggunakan narasi nasionalisme untuk mengecualikan atau mendiskreditkan pihak lain, seperti kelompok minoritas, dengan dalih “melindungi identitas nasional.” Kerap juga terjadi penyalahgunaan kata “bangsa” untuk merujuk pada kelompok sendiri demi menyudutkan kelompok lain, seolah-olah mereka berada di luar definisi bangsa. Ini menunjukkan bahwa ekspresi nasionalisme yang dangkal dapat disalahgunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan.
Nasionalisme kosmetik sering dipandang sebagai antitesis dari nasionalisme sejati. Nasionalisme sejati berakar pada komitmen nyata untuk memajukan bangsa melalui tindakan, pengorbanan, dan tanggung jawab kolektif. Ia tercermin dalam kerja keras, inovasi, integritas, serta kepedulian terhadap isu-isu seperti pendidikan, lingkungan, dan keadilan sosial. Nasionalisme sejati tidak sekadar merayakan kejayaan masa lalu, tetapi juga membangun visi untuk masa depan yang lebih baik. Sebaliknya, nasionalisme kosmetik lebih menyerupai tren atau hobi yang tidak menuntut pengorbanan berarti. Ia mudah dipamerkan, namun kosong dari esensi. Jika nasionalisme sejati adalah pohon yang berakar kuat dan berbuah lebat, nasionalisme kosmetik hanyalah bunga plastik yang indah di pandangan, tetapi tak memiliki kehidupan.
Fenomena nasionalisme kosmetik memiliki sejumlah konsekuensi. Ia berisiko mengikis makna sejati dari nasionalisme. Ketika cinta tanah air hanya diukur dari atribut atau ritual, nilai-nilai luhur seperti solidaritas, keadilan, dan tanggung jawab sebagai warga negara menjadi terpinggirkan.
Generasi muda mungkin terjebak dalam persepsi bahwa nasionalisme cukup diwujudkan dengan mengenakan seragam batik atau mengikuti upacara, tanpa memahami bahwa nasionalisme sejati menuntut kontribusi nyata.
Selain itu, nasionalisme kosmetik dapat memicu polarisasi, terutama di era media sosial. Mereka yang tidak ikut dalam euforia simbolik tertentu—seperti mengganti foto profil atau menggunakan tagar tertentu—sering dicap sebagai “kurang nasionalis.” Penyalahgunaan narasi “bangsa” untuk mengecualikan kelompok lain semakin memperparah polarisasi, menciptakan perpecahan alih-alih persatuan. Ketika nasionalisme menjadi kedok untuk rasisme implisit atau ujaran kebencian, ia dapat memperdalam ketegangan sosial dan merusak harmoni antarkelompok dalam masyarakat.
Terakhir, fokus pada simbol dan seremoni dapat mengaburkan perhatian terhadap masalah-masalah mendasar yang dihadapi bangsa, seperti korupsi, kemiskinan, atau kerusakan lingkungan. Energi yang seharusnya digunakan untuk mencari solusi justru terserap dalam kegiatan seremonial yang dangkal.
Nasionalisme kosmetik mencerminkan tantangan zaman modern, di mana media sosial dan budaya instan sering membentuk cara kita mengekspresikan identitas nasional. Fenomena ini menunjukkan bahwa cinta terhadap tanah air tidak cukup diwujudkan melalui simbol atau seremoni, tetapi memerlukan tindakan nyata—seperti menjaga kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, berkontribusi pada komunitas, hingga berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.
Nasionalisme bukan sekadar mengibarkan bendera atau menyanyikan lagu kebangsaan, tetapi tentang bagaimana seseorang menjalani hidup sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Dengan demikian, nasionalisme sejati menjadi fondasi kokoh yang membawa bangsa menuju masa depan yang lebih baik, bukan sekadar kosmetik yang memudar seiring waktu.