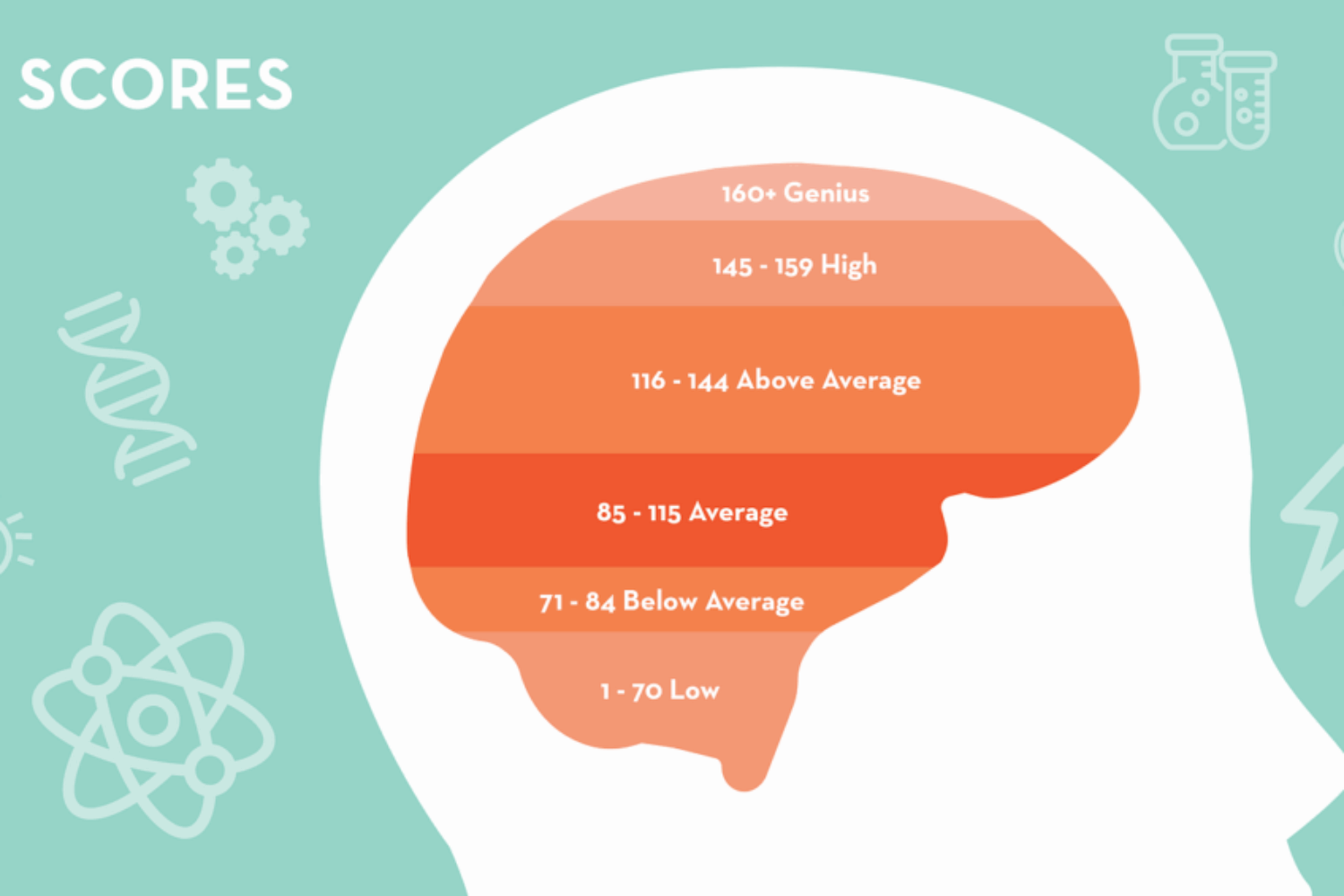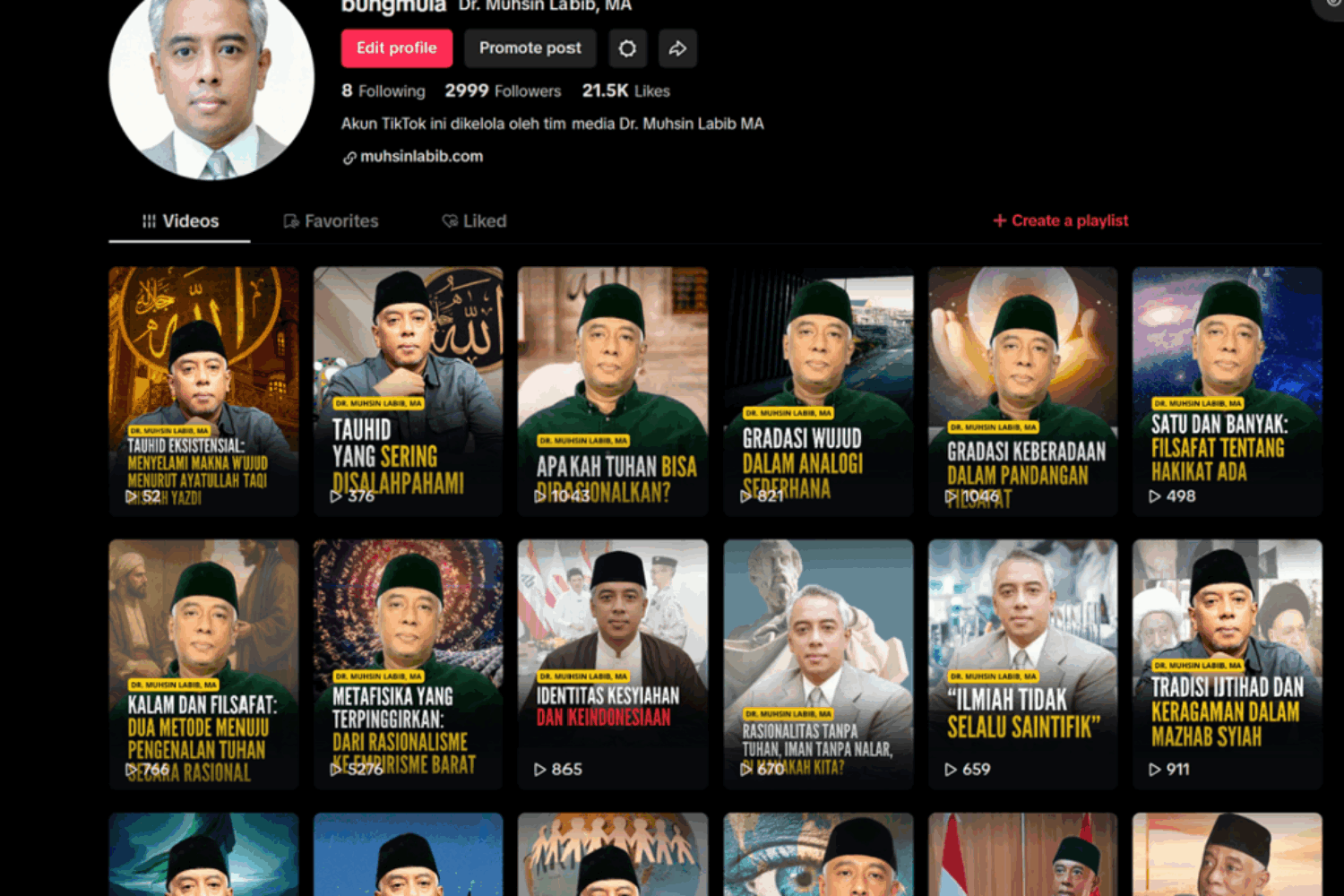Di tengah gemuruh konflik geopolitik yang membelah dunia, sebuah anggapan berbahaya merayap di antara kita, menyebar bak virus di dunia maya: menyamakan Iran dan Israel sebagai dua entitas zalim, bahkan kafir, yang terlibat dalam konflik tanpa pemenang yang benar. Anggapan ini, yang kerap diucapkan dengan nada sinis atau disamarkan dalam narasi netralitas, mencerminkan krisis moral dan intelektual yang lebih dalam—kurangnya empati dan keengganan untuk memahami kompleksitas situasi di tengah banjir informasi era digital.
Mari kita bedah anggapan ini dengan pisau analisis yang tajam namun anggun, sembari menaburkan sedikit garam sindiran pada fenomena yang lebih luas: bagaimana kita, sebagai umat Islam, merespons konflik global yang melibatkan saudara-saudara kita di Palestina dan Iran, di tengah kelelahan empati dan fragmentasi umat.
- Ketiadaan Dasar Historis dan Moral
Pertama, menyamakan Iran dan Israel sebagai dua entitas zalim tidak memiliki dasar historis atau moral yang kuat dalam konteks perjuangan umat Islam. Israel, dengan sejarah panjang penjajahan terhadap Palestina, pembantaian warga sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terdokumentasi, telah menjadi simbol opresi sistematis terhadap umat Islam di kawasan itu. Sejak pendudukan 1948, ratusan ribu warga Palestina telah kehilangan rumah, tanah, dan nyawa mereka akibat agresi militer Israel, yang didukung oleh kekuatan Barat seperti Amerika Serikat dan sekutu Arab tertentu.
Sebaliknya, Iran, meskipun sering dikritik karena kebijakan politiknya atau perbedaan teologis dengan mayoritas Sunni, telah memposisikan diri sebagai salah satu dari sedikit negara yang secara konsisten mendukung perjuangan Palestina melawan penjajahan Israel. Iran memberikan dukungan moral, politik, dan kadang-kadang militer kepada kelompok-kelompok perlawanan di Palestina dan Lebanon, di saat banyak negara lain memilih diam atau bahkan berkompromi dengan Israel. Menyamakan keduanya sebagai “zalim” atau “kafir” mengabaikan fakta bahwa satu pihak adalah penindas yang terbukti, sementara pihak lain, terlepas dari kekurangannya, berjuang melawan hegemoni global untuk membela umat Islam yang tertindas.
Anggapan ini adalah produk dari kecemasan modern, lahir dari polarisasi geopolitik dan narasi sektarian yang diperparah oleh media sosial. Ia mencerminkan sinisme terhadap konflik yang kompleks, di mana semua pihak dihakimi sama bersalah tanpa mempertimbangkan konteks sejarah atau realitas di lapangan.
- Sektarianisme yang Menyamar sebagai Netralitas
Kedua, anggapan ini sering kali digunakan untuk memosisikan lebih dari 500 juta umat Islam Syiah, termasuk Iran, sebagai golongan zalim saat mereka berkonfrontasi dengan Israel—musuh tak seagama yang arogan—demi membela kelompok Muslim lain yang ditindas, seperti rakyat Palestina, yang tidak mendapat cukup dukungan dari kelompok semazhab. Dalam konteks ini, menyamakan Iran dengan Israel sama saja dengan berkoalisi dengan penindas—sebuah ironi yang menyakitkan. Narasi negatif terhadap sesama Muslim, khususnya Syiah, yang nyata berkorban dalam perjuangan melawan Israel, tak kalah sadisnya, bahkan lebih keji, dari rudal-rudal yang ditembakkan oleh jet tempur F-35 Israel terhadap warga Palestina dan pejuang perlawanan.
Lebih ironis lagi, anggapan keji ini dijustifikasi dengan teks doa yang pada dasarnya netral namun sengaja dialamatkan kepada Iran dan umat Muslim Syiah yang bertempur melawan Israel serta berkorban demi membela rakyat Palestina yang tak bermazhab Syiah. Teks doa tersebut berbunyi: “Ya Allah, musnahkanlah orang-orang zalim dengan orang-orang zalim lainnya, dan keluarkanlah kami dari antara mereka dalam keadaan selamat.” Doa ini, yang tidak memiliki jejak dalam tradisi suci Islam—tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak terucap oleh para sahabat, dan tidak tercatat dalam hadis sahih seperti Sahih Bukhari atau Muslim maupun kitab doa seperti Al-Adzkar karya Imam Nawawi—menjadi alat untuk memvonis pihak-pihak yang bertikai sebagai “zalim” tanpa analisis mendalam.
Frasa “musnahkan orang-orang zalim dengan orang-orang zalim” mencerminkan sinisme, sementara permohonan “keluarkan kami dari antara mereka” menunjukkan keinginan untuk lepas dari konflik tanpa tanggung jawab moral. Ketika doa ini sengaja diarahkan untuk mencela Iran dan pejuang Syiah, ia menjadi lebih mematikan dari rudal, karena memperdalam perpecahan umat dan melemahkan solidaritas terhadap perjuangan Palestina.
Ketika seorang Muslim di Gaza terbunuh oleh bom Israel, atau ketika pejuang Syiah di Iran dan sekutunya menghadapi sanksi dan tekanan global karena mendukung Palestina, apakah kita akan menanyakan mazhab atau aliran mereka sebelum merasakan empati? Anggapan ini, yang diperparah oleh penyalahgunaan doa, membebaskan kita dari beban berpikir kritis, seolah dunia dapat dibagi rapi menjadi dua kubu yang sama-sama jahat, tanpa ruang untuk memahami kerumitan kemanusiaan atau solidaritas umat. Padahal, Al-Quran dalam Al-Maidah ayat 8 dengan tegas memerintahkan: “Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa”.
Nabi Muhammad SAW juga bersabda: “Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan yang saling menguatkan.” Hadis ini tidak mengenal sekat mazhab atau aliran ketika berbicara tentang solidaritas umat. Namun, anggapan yang menyamakan Iran dan Israel, apalagi yang dijustifikasi dengan doa apatis, justru membangun tembok pemisah di antara sesama Muslim, menjadikan perbedaan teologis sebagai alasan untuk mengabaikan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina atau perjuangan Iran melawan hegemoni Barat.
- Arogansi Moral dalam Jubah Netralitas
Ketiga, mereka yang menyamakan Iran dan Israel, sering kali dengan dalih doa yang dimanipulasi, memosisikan diri sebagai pihak yang netral, seolah-olah mereka berdiri di atas semua pihak sebagai penutur kebenaran yang objektif. Dalam konstruksi mental ini, “kami” adalah kelompok yang bersih, bebas dari keterlibatan, sementara “mereka”—baik Iran maupun Israel—adalah entitas yang kotor dan pantas dikecam. Pengucap doa semacam itu bahkan menyatakan diri sebagai “hamba pilihan” yang layak mendapat perlindungan ilahi, sementara pihak lain dihakimi sebagai massa yang pantas dimusnahkan. Arogansi moral ini berbahaya karena menciptakan ilusi superioritas tanpa introspeksi.
Dalam ajaran Islam, kerendahan hati (tawadhu) adalah nilai yang sangat ditekankan. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barangsiapa yang merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan meninggikannya.” Dengan menyamakan Iran—yang, meski tidak sempurna, mendukung perjuangan umat Islam—dengan Israel, yang secara konsisten menindas rakyat Palestina, kita tidak hanya gagal berlaku adil, tetapi juga kehilangan kerendahan hati untuk mengakui kompleksitas situasi.
- Bystander Morality dan Kelelahan Empati
Keempat, anggapan ini mencerminkan kecenderungan yang oleh psikolog sosial disebut bystander effect—keengganan untuk bertindak ketika orang lain menderita, terutama ketika kita merasa tidak bertanggung jawab secara personal. Dalam konteks moral, ini menjadi semacam bystander morality: mengambil sikap “netral” untuk menghindari tanggung jawab moral dalam mendukung perjuangan Palestina atau solidaritas dengan Iran yang menghadapi tekanan global. Doa apatis yang memohon keselamatan pribadi tanpa empati—“selamatkan kami yang baik dan cakep dari antara mereka”—memperkuat sikap ini, menawarkan pelarian spiritual tanpa keterlibatan nyata. Ironi ini nyaris puitis: sebuah doa yang seolah suci, tetapi digunakan untuk menutupi ketidakpedulian.
Di era media sosial, kita dibombardir dengan informasi tentang penderitaan umat Islam—dari pemboman Israel di Gaza hingga sanksi ekonomi yang melumpuhkan Iran. Akibatnya, banyak di antara kita mengalami compassion fatigue—kelelahan empati yang mendorong kita mencari jalan pintas untuk “merespons” tanpa benar-benar terlibat.
Menyamakan Iran dan Israel, apalagi dengan dalih doa yang dimanipulasi, adalah salah satu jalan pintas itu: sebuah cara untuk terlihat peduli tanpa harus memahami akar konflik atau mengambil sikap yang mungkin kontroversial.
- Konteks Zaman: Fragmentasi Umat dan Sektarianisme
Anggapan ini, yang diperparah oleh penyalahgunaan doa, tidak lepas dari konteks zaman kita yang unik. Media sosial memperkuat narasi sektarian, di mana perbedaan mazhab—khususnya antara Sunni dan Syiah—dimanfaatkan untuk memecah belah umat Islam. Ketika rakyat Palestina menghadapi agresi Israel atau Iran berjuang melawan tekanan AS dan sekutu Arabnya, sebagian umat justru terjebak dalam debat teologis yang tidak produktif, mengkategorikan saudara-saudara mereka sebagai “zalim” atau bahkan “kafir” karena perbedaan mazhab.
Yang lebih memprihatinkan, anggapan ini mencerminkan fragmentasi umat yang semakin dalam. Kita lebih mudah berempati kepada pihak lain daripada kepada Muslim yang berbeda mazhab, seperti Syiah di Iran yang berjuang melawan hegemoni Barat atau Sunni di Palestina yang menghadapi penjajahan Israel. Doa yang dimanipulasi untuk menjustifikasi sikap ini menjadi manifestasi dari keinginan untuk tetap terlihat “peduli” tanpa harus memahami kompleksitas situasi. Ini adalah spiritualitas fast food untuk jiwa yang lapar namun malas mengunyah, sebuah produk zaman yang menginginkan solusi instan untuk masalah yang kompleks.
- Alternatif yang Lebih Bermartabat
Alih-alih terjebak dalam anggapan yang menyamakan Iran dan Israel atau doa apatis yang dimanipulasi, tradisi Islam menawarkan pendekatan yang lebih bermartabat dan konstruktif:
Pertama, berdoa untuk keadilan, bukan untuk kehancuran. Rasulullah SAW mengajarkan: “Allahumma ahdinii fii man hadayta” (Ya Allah, berilah aku petunjuk di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk).
Kedua, berusaha memahami akar masalah dengan bijak. Al-Quran memerintahkan: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti” (QS. Al-Hujurat: 6).
Ketiga, mengambil sikap yang proporsional berdasarkan pemahaman yang mendalam, bukan emosi sesaat atau tekanan sosial, baik dalam mendukung perjuangan Palestina maupun solidaritas dengan Iran melawan penindasan global.
Penutup: Menuju Solidaritas yang Utuh
Menyamakan Iran dan Israel sebagai dua entitas zalim adalah cermin dari krisis zaman kita: penuh semangat namun cacat, reaktif namun tidak reflektif. Anggapan ini, apalagi ketika dijustifikasi dengan doa yang dimanipulasi, bukan hanya kejahatan intelektual, tetapi juga pengkhianatan terhadap solidaritas umat Islam. Ia mengingatkan kita bahwa tanggung jawab moral kita sebagai Muslim adalah menghadapi dunia dengan keberanian, kejernihan, dan empati yang melampaui sekat-sekat sektarian.
Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barangsiapa yang tidak menyayangi manusia, maka dia tidak akan disayangi (oleh Allah).” Hadis ini tidak mengenal pembatasan mazhab atau aliran. Dalam tradisi sufisme, konsep fana fi Allah—lebur dalam Allah—mengajarkan kita untuk menghadapi dunia dengan hati yang lapang, merangkul sesama Muslim tanpa memandang perbedaan teologis.
Zaman ini memang sarat dengan konflik dan intrik, tetapi respons kita terhadapnya akan menentukan karakter spiritual kita. Kita bisa memilih menjadi bystander yang apatis, menyamakan Iran dan Israel untuk menghindari tanggung jawab moral, atau memperparah perpecahan dengan doa yang disalahgunakan. Atau kita bisa memilih menjadi manusia yang utuh—yang mampu merasakan empati tanpa kehilangan akal sehat, yang mampu mendukung perjuangan Palestina dan solidaritas dengan Iran tanpa terjebak dalam perangkap sektarianisme.
Darah Muslim yang tertumpah di Palestina atau perjuangan umat Syiah di Iran melawan Israel dan sekutunya adalah darah saudara kita, terlepas dari perbedaan mazhab. Rudal yang menghantam mereka tidak menanyakan aliran teologis mereka. Mengapa kita harus melakukannya?
Terlepas apakah anggapan ini disengaja atau tidak, sekadar menganggap konfrontasi antara Israel dan Iran sebagai konflik sesama zalim, bahkan sesama kafir, adalah kejahatan. Anggapan ini menjadi lebih mematikan dari lusinan rudal yang ditembakkan dari F-35 bila ditujukan kepada Iran dan umat Muslim Syiah yang sedang berjuang sendirian melawan Israel, AS, serta sekutu Barat dan Arabnya.
Pilihan ada di tangan kita.
Seperti yang dikatakan Albert Einstein: “Dunia ini berbahaya bukan karena orang-orang yang berbuat jahat, tetapi karena orang-orang yang melihat dan tidak berbuat apa-apa.” Lebih berbahaya lagi ketika yang melihat justru bersukacita atas penderitaan sesama karena perbedaan yang seharusnya tidak memisahkan kita.
Meski Iran dan umat Muslim Syiah cukup kuat tanpa bantuan Rusia, China dan umat Muslim, karena mempunya turbin spirit Karbala dan Asyura, bersikap adil tetaplah baik dan perlu bagi umat yang tak ikut bertempur.