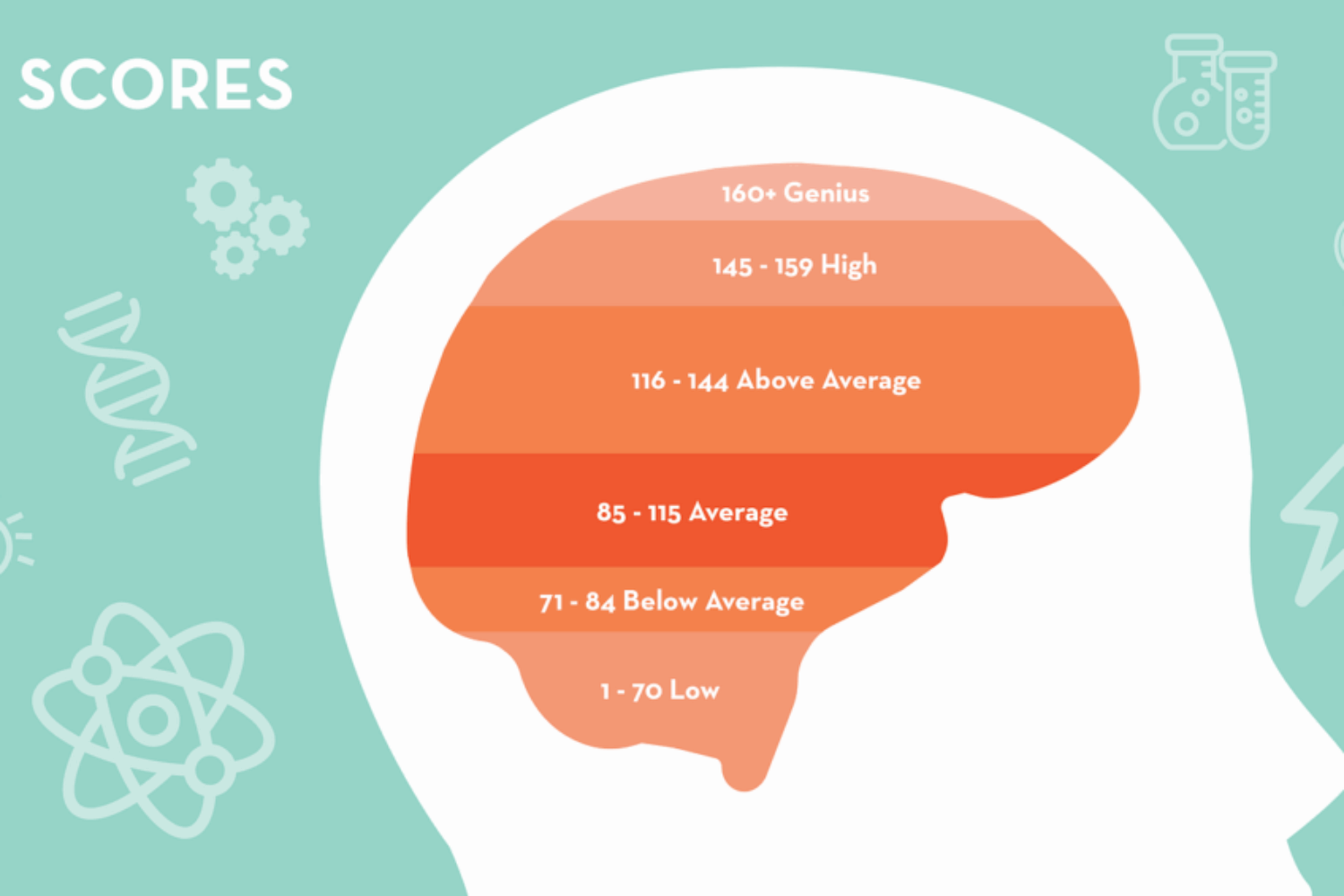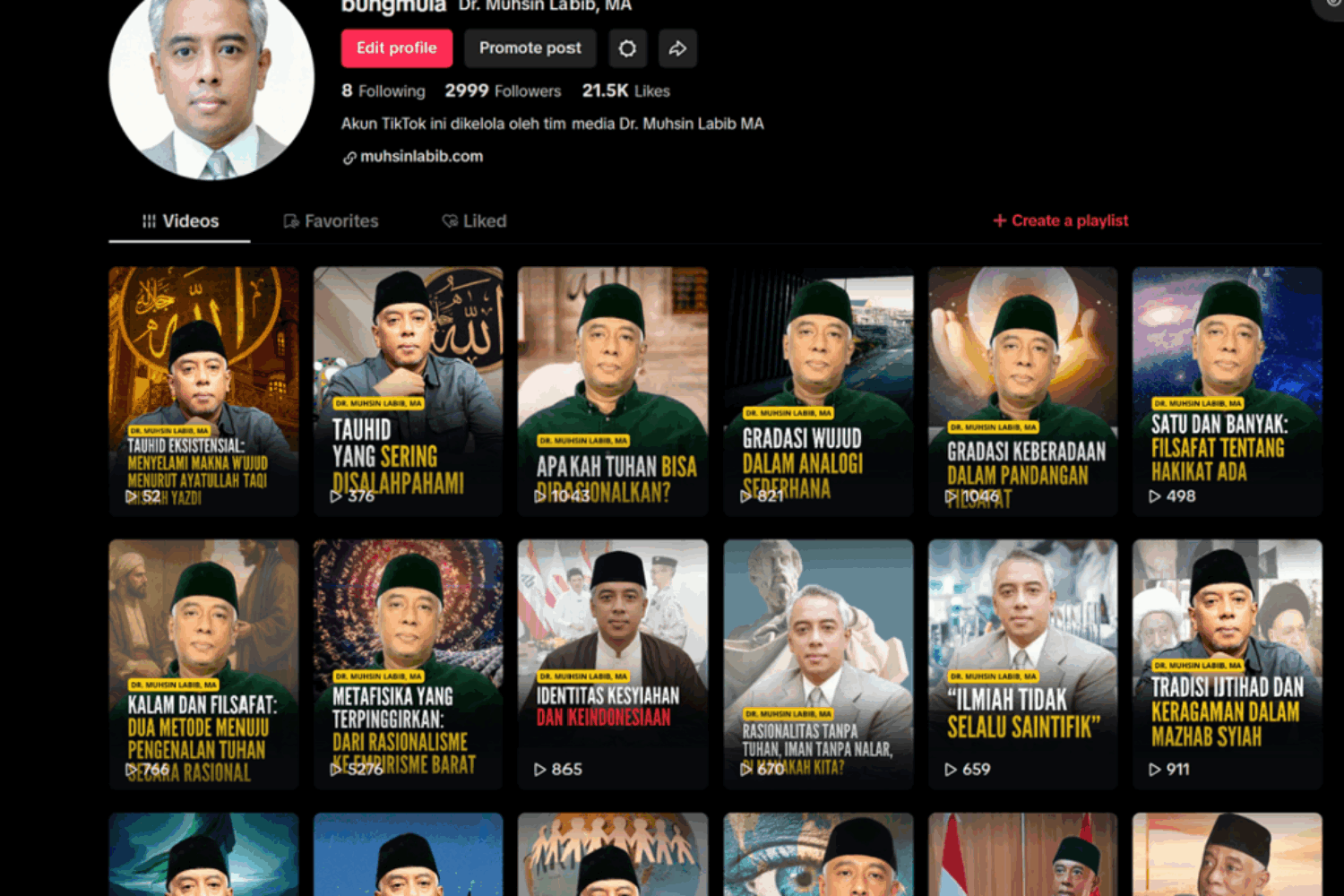Angin Damaskus bertiup, membawa debu dan aroma ketakutan, bukan wangi rempah pasar. Di jantung istana megah yang menaungi kekuasaan rapuh, rombongan tawanan melangkah, mengoyak topeng kemunafikan. Para wanita Ahlul Bait, dengan kain compang-camping bernoda darah suci Al-Husain, menuntun putra-putra harapan di samping bayang syuhada Karbala. Mata mereka merah, namun kering; tubuh lelah, namun tulang punggung tegak bagai pohon kurma yang menantang badai.
Yazid bersemayam di singgasananya, mata penuh kemenangan busuk menyapu rombongan. Ia mencari kehancuran di wajah-wajah itu, tanda-tanda keputusasaan yang akan memuliakan kejayaannya. Pandangannya tertancap pada Zainab binti Ali—tiang ketegaran di pusat badai, saksi kepala saudaranya di ujung tombak, saksi darah suci yang menyiram padang Karbala.
“Hai Zainab!” serunya, suara menggelegar penuh ejekan. “Bagaimana kau melihat derita yang kau alami? Bagaimana perasaanmu setelah Al-Husain dan seluruh keluarganya terkepung, terbunuh, lalu kalian digiring sebagai tawanan?” Setiap kata bagai pisau bermata dua: mengiris memori, memamerkan kemenangan.
Istana membeku. Para pembesar menanti tangis, ratapan, atau getar ketakutan—drama yang akan mengukuhkan keperkasaan Yazid. Zainab berdiri. Tubuh kurusnya memancar cahaya keteguhan. Wajah pucatnya tak berkerut. Matanya menembus cakrawala. Debu Karbala membingkai jiwa yang tak tersentuh, jiwa yang telah menyatu dengan makna abadi. Ia menatap lurus Yazid, tatapan hakim menghadapi terdakwa. Suara jernihnya memecah kesunyian, menggetarkan pilar-pilar istana: “Demi Allah! Aku tak melihat dalam segala yang menimpa kami… kecuali… KEINDAHAN SEMATA!”
Kalimat itu menggantung, tajam bagai pedang cahaya, menghujam jantung kesombongan Yazid.
Keindahan? Di puing kehancuran, di bawah belenggu tawanan, setelah neraka Karbala? Ya! Bagi Zainab, keindahan itu nyata, abadi, dan tak terjangkau oleh singgasana duniawi. Keindahan itu adalah:
1 Kebenaran yang Berkibar Tinggi: Darah syuhada Karbala menulis sejarah keadilan dengan tinta emas, menolak dipadamkan oleh pedang tirani.
2 Keteguhan Tak Tergoyahkan: Ketabahan di kegelapan adalah pelita kenabian yang menyala abadi, menerangi jalan umat.
3 Pengorbanan sebagai Cinta Tertinggi: Setiap tetes darah Husain adalah benih kebangkitan, menumbuhkan pohon keabadian.
4 Tugas Suci yang Mulia: Rantai di pergelangan menjadi kalung risalah; panggung penghinaan berubah menjadi mimbar kebenaran.
Keindahan Zainab bukan sekadar pernyataan kemenangan rohani. Ia adalah cerminan harmoni filosofis antara femininitas dan maskulinitas, dua kutub yang saling melengkapi dalam revolusi Karbala. Femininitas Zainab—yang lembut namun tak pernah lemah, penuh kasih namun teguh—adalah pasangan setara maskulinitas Al-Husain, yang gagah berani dan rela berkorban.
Dalam filsafat eksistensial, maskulinitas sering diidentifikasi dengan aksi, keberanian, dan pengurbanan fisik, sementara femininitas diasosiasikan dengan ketahanan batin, kasih sayang, dan kepekaan rohani. Namun, Karbala menolak dikotomi sempit ini. Di padang pasir berdarah, Al-Husain menjelmakan maskulinitas suci melalui pedangnya yang memperjuangkan keadilan, sementara Zainab mewujudkan femininitas ilahi melalui kata-katanya yang mengguncang singgasana. Keduanya adalah dua sisi dari mata uang kebenaran yang sama: pengorbanan Husain adalah nyala api, dan keteguhan Zainab adalah bara yang tak pernah padam.
Femininitas Zainab bukanlah kelembutan yang pasif. Ia adalah kekuatan yang melahirkan keabadian, sebagaimana bumi yang subur menerima benih untuk menumbuhkan kehidupan baru. Dalam tradisi filosofis, bumi sering dipandang sebagai simbol feminin yang merangkul dan memelihara, namun juga kokoh dan tak tergoyahkan. Zainab adalah bumi Karbala: ia menampung darah syuhada, menjaga risalah, dan menyuburkan kebenaran untuk generasi mendatang. Maskulinitas Husain, bagai langit yang menurunkan hujan pengorbanan, menemukan keseimbangan sempurna dalam femininitas Zainab, yang mengubah hujan itu menjadi sungai kehidupan abadi.
Di istana Yazid, Zainab bukan sekadar wanita yang berbicara; ia adalah suara kemanusiaan yang menolak ditundukkan. Kata-katanya, “Keindahan Semata!”, adalah deklarasi bahwa femininitas dan maskulinitas, dalam harmoni suci, mampu mengguncang fondasi tirani. Yazid, dengan kekuasaannya yang semu, hanya memahami keperkasaan duniawi—pedang, takhta, dan darah. Ia buta terhadap keindahan yang lahir dari perpaduan pengorbanan heroik Husain dan keteguhan visioner Zainab. Femininitas Zainab adalah cermin yang memantulkan kelemahan Yazid: seorang tiran yang tak pernah memahami bahwa kebenaran sejati tidak memerlukan singgasana, melainkan hati yang hidup dan jiwa yang merdeka.
“Keindahan Semata!” adalah ledakan cahaya di istana gelap Yazid, deklarasi kemenangan abadi. Kata-kata itu mengoyak topeng sang tiran, menyingkap kebobrokan di balik kemilau emas. Di panggung duniawi yang penuh gemerlap, seorang wanita berbelenggu menyatakan keindahan tertinggi: keindahan yang lahir dari api pengorbanan, bersinar di atas puing tirani, dan mengguncang zaman. Harmoni femininitas dan maskulinitas dalam revolusi Karbala adalah bukti bahwa kebenaran tidak mengenal gender, tetapi menuntut kesetiaan jiwa—jiwa yang, seperti Zainab dan Husain, menjelma sebagai pelita abadi bagi umat manusia.