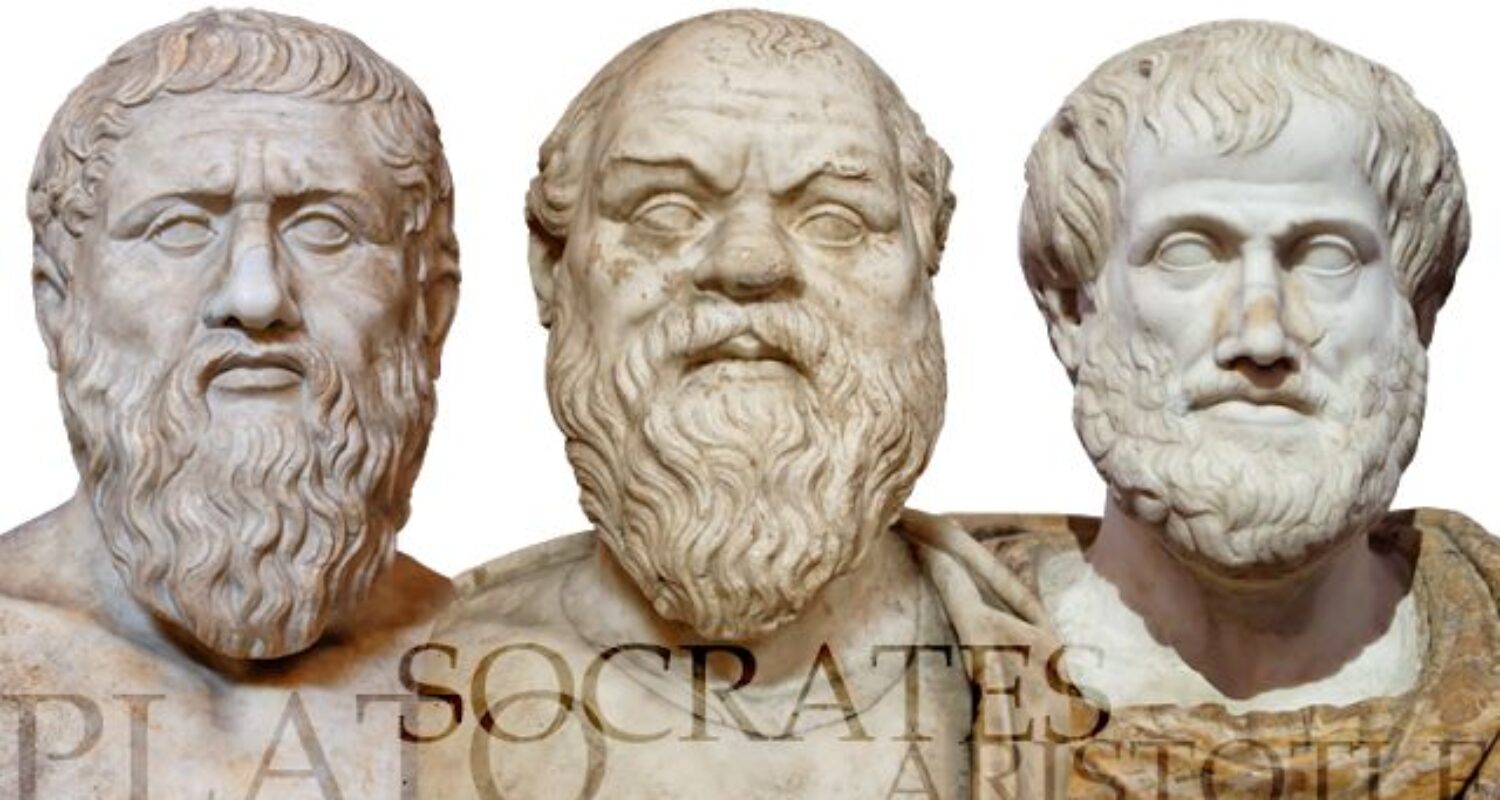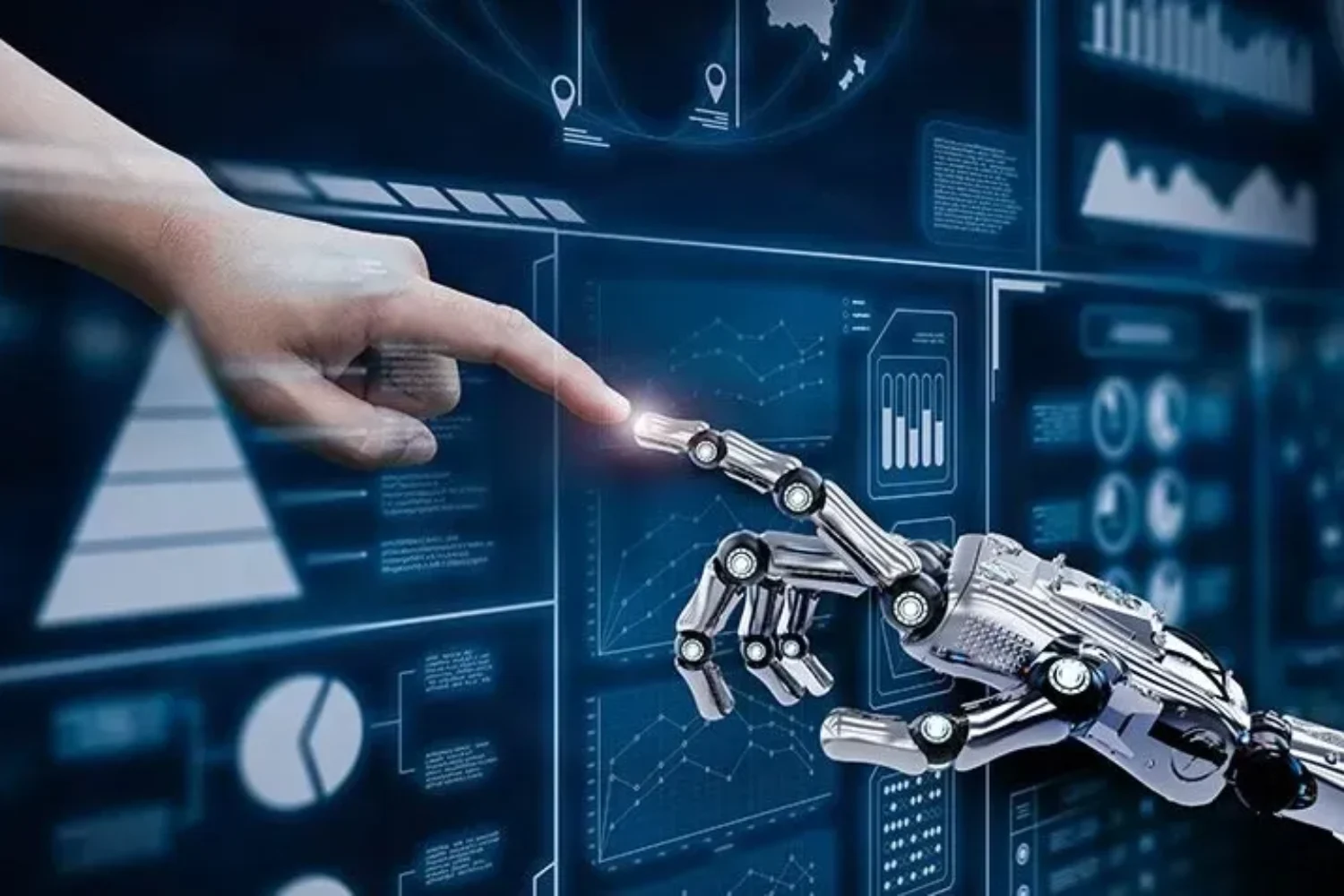Mengapa manusia memproklamasikan kemerdekaan dari marga satwa dan mendirikan spesies mandiri dan enggan disebut hewan dan binatang? Bukankah juga mengalami realitas terlebih dahulu melalui pengalaman pra-konseptual sebelum indera menangkapnya sebagai konsep partikular?
Jawabannya terletak pada kemampuannya mengabstraksikan realitas ke dalam lapisan-lapisan universal yang kompleks—sebuah proses intelektual yang membedakan manusia dari makhluk lain. Meskipun sama-sama mengalami dunia secara pra-konseptual, manusia mampu mengolah konsep partikular menjadi universal yang esensial, dan membangun sistem logika-bahasa sebagai instrumen penalaran.
Mayoritas manusia, dalam keseharian pengetahuannya, cenderung menganut paham esensialisme, yaitu menganggap bahwa eksistensi itu sendiri adalah esensi. Hal ini terjadi karena mereka tidak menempatkan eksistensi sebagai realitas yang tak terjangkau oleh indera dan nalar konseptual, sedangkan esensi justru hadir dalam spektrum keragaman yang dapat dikenali melalui kedua instrumen itu. Dari sini, manusia menciptakan terma-terma universal untuk mengodifikasi konsep-konsep universal primer sebagai sistem penalaran logis yang berfungsi sebagai fondasi kognisi. Hampir seluruh manusia pada akhirnya mempraktikkan sistem kognisi epistemik ini secara otomatis.
Tiga tingkat abstraksi—identifikasi esensial, kesadaran eksistensial, serta penalaran logis—menjadi penanda utama proses filosofis manusia. Namun, lapisan ini sekaligus menjadi filter yang menjauhkan manusia dari pengalaman konkret realitas. Semakin kaya pengetahuan konseptual, semakin besar pula risiko keterasingan manusia dari realitas yang langsung; seperti halnya seorang ahli yang sering terpisah dari pengalaman murni objek yang dikajinya.
Masalah muncul ketika kelompok tertentu mulai mempersoalkan validitas keragaman sebagai eksistensi sejati. Perdebatan pun tak terelakkan, mengemuka antara kubu esensialisme dan eksistensialisme—dalam pengertian primordial, bukan eksistensialisme modern ala Sartre—atau antara pluralisme (yang tanpa sadar cenderung memihak esensialisme) dan monisme (yang tidak sengaja menafikan eksistensi dari keragaman entitas). Pada titik inilah manusia menjadi benar-benar filosofis: ketika ia bergerak mencari konsep universal eksistensial dan menantang batas-batas sistem pengetahuannya sendiri.
Paradoks Homo philosophicus terletak pada kecenderungan memaksakan sistem logika pada realitas: bila kenyataan tidak sesuai konsep, maka realitas dianggap “belum dipahami.” Namun, hanya segelintir manusia—yang berani menembus batas esensi dan mengupayakan pemahaman eksistensial dari pengalaman murni—layak menyandang predikat Homo philosophicus sejati.
Kesadaran akan keterpisahan manusia dari realitas sesungguhnya merupakan hasil dari abstraksi itu sendiri. Manusia tidak dapat kembali ke kepolosan epistemik awal, karena setiap pengetahuan telah mengandaikan jarak. Namun, justru dalam kesadaran akan keterbatasan inilah terletak potensi transendensi manusia.
Jati diri Homo philosophicus tidak terletak pada tumpukan pengetahuan, melainkan pada hasrat untuk bertanya dan keberanian mempertanyakan validitas abstraksinya sendiri—disertai pengakuan akan kebenaran yang melampaui batas logika manusia. Keunikan manusia muncul ketika ia mengakui keterbatasan dan membuka diri terhadap kemungkinan pemahaman yang lebih luas.
Pendekatan transendental memandang pengetahuan sejati sebagai penyatuan eksistensial antara subjek dan objek: lapisan-lapisan abstraksi bukan lagi sekadar penghalang, melainkan jendela menuju dialog yang otentik dengan realitas. Objektivitas, dalam konteks Homo philosophicus, adalah penyelarasan eksistensial, bukan penyangkalan subjektivitas.
Dengan demikian, Homo philosophicus adalah manusia yang tersesat dalam konseptualisasi, namun selalu mencari jalan transformasi diri melalui setiap perjumpaan pengetahuan. Pemahaman sejati menjadi perluasan eksistensi lewat penyatuan dengan realitas yang lain.
Inilah paradoks manusia: ditakdirkan berfilsafat, namun kebijaksanaan tertinggi justru ditemukan dalam kesadaran akan keterbatasan dan keterbukaan pada kekayaan realitas itu sendiri.