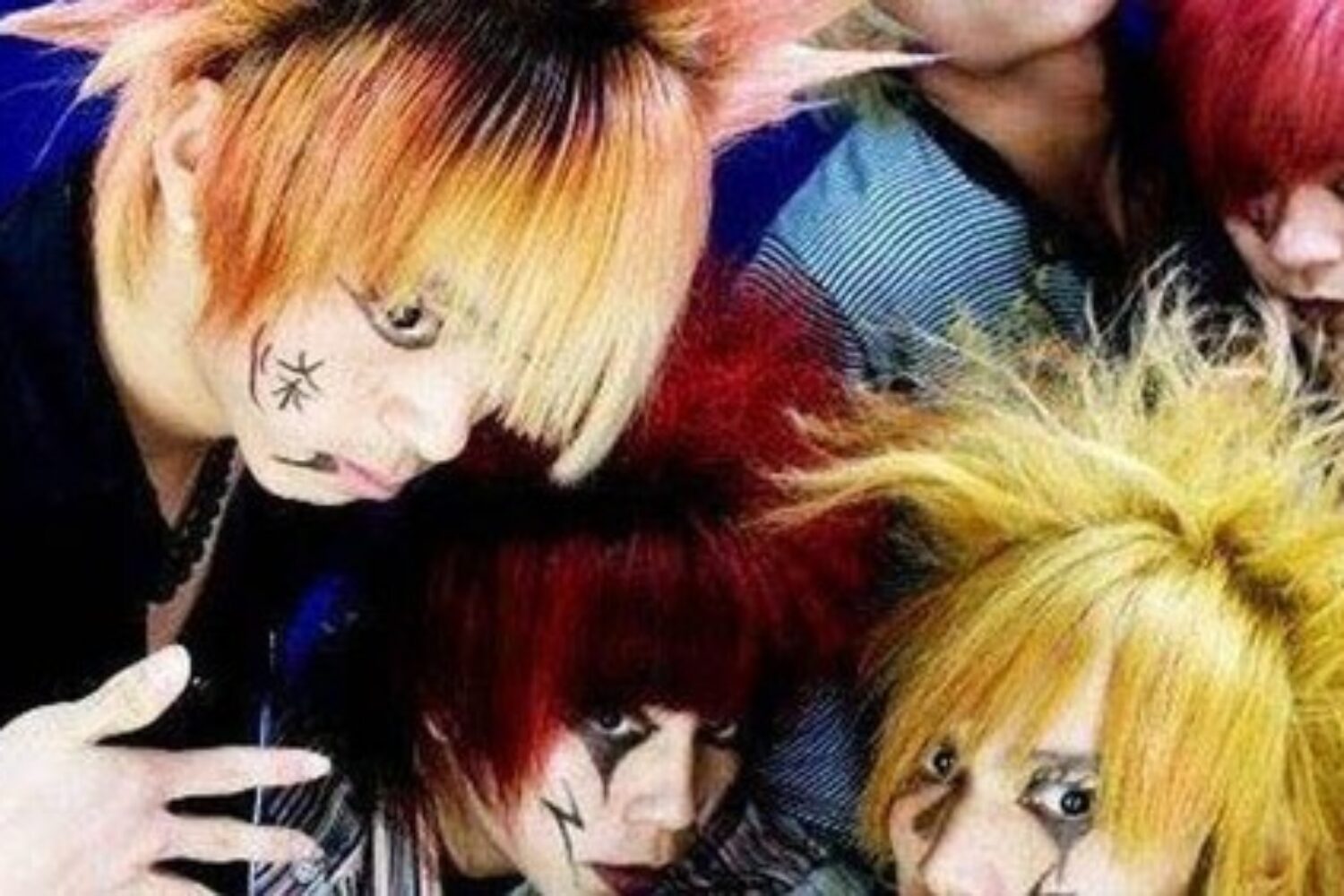Di era ketika algoritma lebih memuja wajah ketimbang substansi, muncul sebuah fenomena yang sama memuakkan sekaligus memilukan: podcaster bermodal rupa. Para pelaku ini bersenjatakan senyum memesona, sudut kamera yang sempurna, dan keberanian tanpa batas untuk naik ke mimbar digital guna membedah isu-isu dunia—yang seringkali hanya mereka ketahui dari judul artikel yang dibaca sekilas lima menit sebelumnya.
Modal utama mereka bertumpu pada keyakinan bahwa ketampanan adalah tiket emas menuju status “pakar dadakan”. Dengan pesona visual sebagai senjata, mereka menggiring penonton untuk mengklik “subscribe”, seolah logika dan pengetahuan hanyalah aksesori opsional dalam dunia konten digital. Mungkin viewer memilih menonton wajah sambil memenuhi dahaga fantasi tapi tak “menonton narasi di balik wajahnya”. Ironisnya, dalam parade kesembronoan ini, korban utama yang terinjak-injak adalah bahasa Indonesia itu sendiri.
Kepercayaan diri mereka ibarat baja tahan karat, seolah kamera depan ponsel adalah sertifikat keahlian universal. Tanpa perlu riset mendalam, tanpa perlu memahami sejarah, apalagi mengasah kemampuan analisis, mereka cukup menyalakan aplikasi rekaman, mengatur pencahayaan untuk menonjolkan tulang pipi, dan mulai berbicara.
Isu kompleks seperti geopolitik, ekonomi mikro, atau filsafat eksistensial diramu ulang menjadi obrolan ringan yang kosong—dibalut dengan bumbu utama: pesona wajah. Logika mereka sederhana namun mengerikan: mengapa harus susah-susah belajar jika senyum manis sudah cukup memikat audiens?
Namun, di balik layar yang tersaji mulus, tersembunyi bencana linguistik yang menyayat hati. Ketika mulut-mulut rupawan itu berbicara, yang keluar bukanlah mutiara kebijaksanaan, melainkan kerikil-kerikil bahasa yang menciderai telinga siapa pun yang masih menghargai literasi. Kengerian gramatikal menjadi ciri khas podcast mereka, dengan penyiksaan kata sambung sebagai menu utama yang disajikan tanpa malu-malu.
Perhatikan bagaimana kata “terhadap” diseret ke mana-mana tanpa belas kasihan: “Pendapat saya terhadap dia sangat terhadap isu ini…” Seolah kata itu adalah lem serba guna yang bisa merekatkan segala hal. Kata “dengan” tak kalah tragis, dipaksa jadi pengisi jeda yang malang: “Saya ke pasar dengan membeli buah dengan yang segar.” Sungguh, sebuah prestasi dalam mengguncang tata bahasa.
Kemudian ada “walaupun” yang terlontar tanpa logika yang jelas, atau “secara” yang disalahartikan sebagai pengganti “tentang”, menghasilkan kalimat mengerikan seperti: “Secara dia sudah pergi, kita harus secara bijaksana.” Kata “atas” pun jadi korban, sering menggantikan “mengenai” seenaknya: “Dia berbicara atas pengalamannya secara personal.” Bahkan “karena” tersesat dalam labirin kalimat mereka: “Podcast saya sukses karena karena saya rajin upload.” Repetisi ini bukan penekanan, melainkan bukti kebingungan.
Kekacauan linguistik ini bukan sekadar salah ucap. Ia adalah cermin dari sikap meremehkan kekayaan bahasa dan proses berpikir itu sendiri. Bahasa yang rusak mencerminkan pikiran yang ceroboh. Ketika kata sambung—jembatan logika antar gagasan—dilempar asal-asalan, itu menunjukkan ketidakpedulian terhadap struktur nalar dan keindahan komunikasi. Mereka tak ambil pusing apakah audiens memahami; yang penting bibir tetap bergerak anggun di depan kamera.
Fenomena ini merupakan penghinaan terhadap literasi. Ia mengajarkan generasi muda bahwa penampilan lebih berharga daripada pengetahuan, bahwa popularitas bisa diraih tanpa usaha intelektual, dan bahwa bahasa boleh diperlakukan sembarangan. Ini adalah kultus kesembronoan yang dibalut filter Instagram. Para podcaster bermodal rupa ini, dengan segala keanggunan visualnya, sejatinya adalah vandal bahasa. Mereka mencoreng tembok kebudayaan kita dengan kesalahan gramatikal dan kesombongan intelektual.
Literasi, kemampuan berbahasa yang tepat, kedalaman analisis, dan penghormatan terhadap pengetahuan—itulah yang seharusnya menjadi modal sejati, jauh melampaui sorotan ring light atau sudut kamera 45 derajat. Jika tidak, kita hanya akan menyaksikan kebangkrutan intelektual massal, di mana yang tersisa hanyalah wajah-wajah tampan yang mengoceh tanpa makna. Ketika kata-kata kehilangan arti, yang tersisa hanyalah kebisingan kosong dalam balutan wajah rupawan—sebuah parodi literasi yang menyedihkan.
Ini juga merupakan bukti bahwa visualisme—anak kandung inferiority complex dari penjajahan purba hingga modern dan cucu materialisme yang pasti ateistik—telah menjebak kita dalam obsesi kesempurnaan yang sempit: kulit mulus, lekuk dagu, dan onggokan daging yang dibonsai demi sorotan kamera.