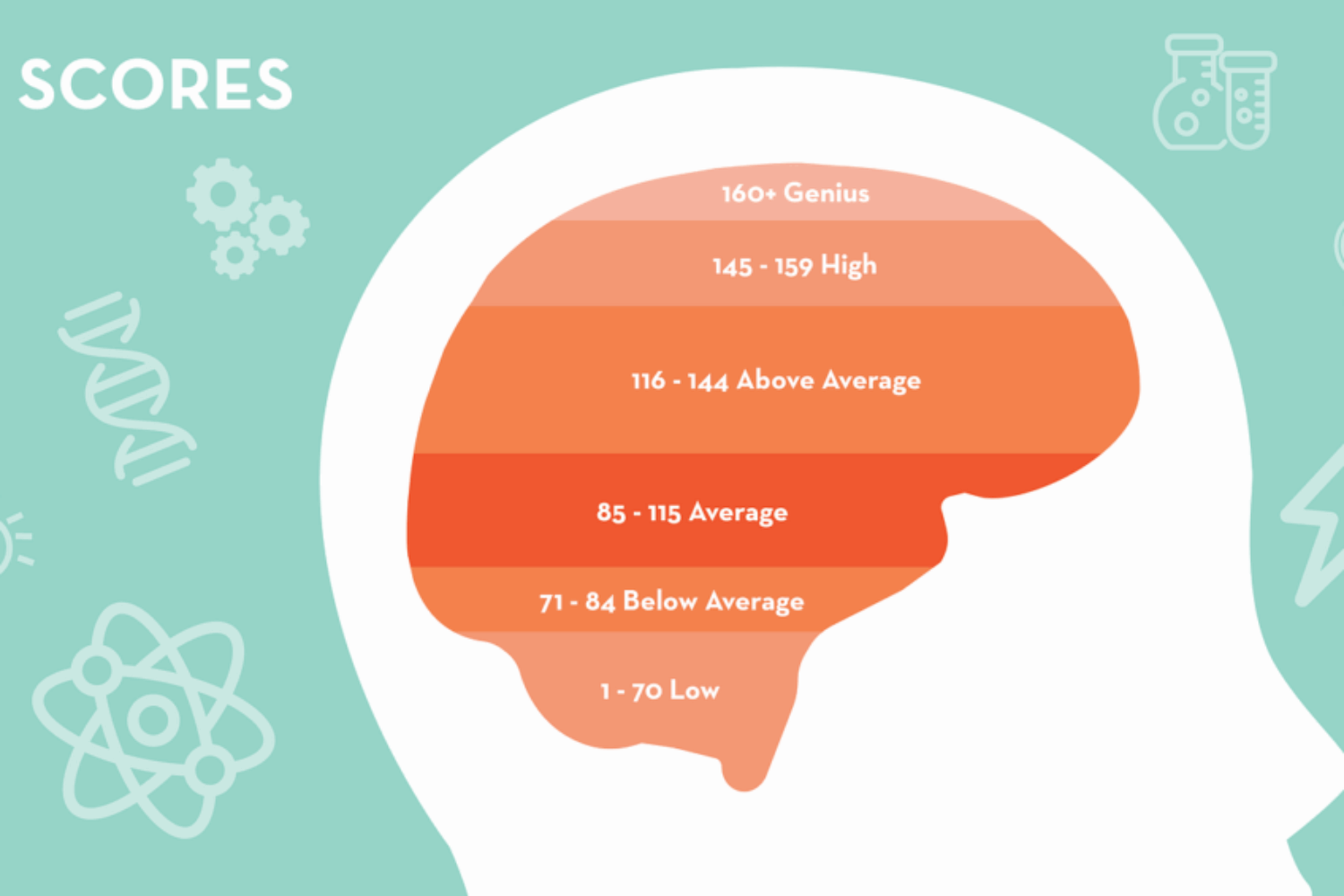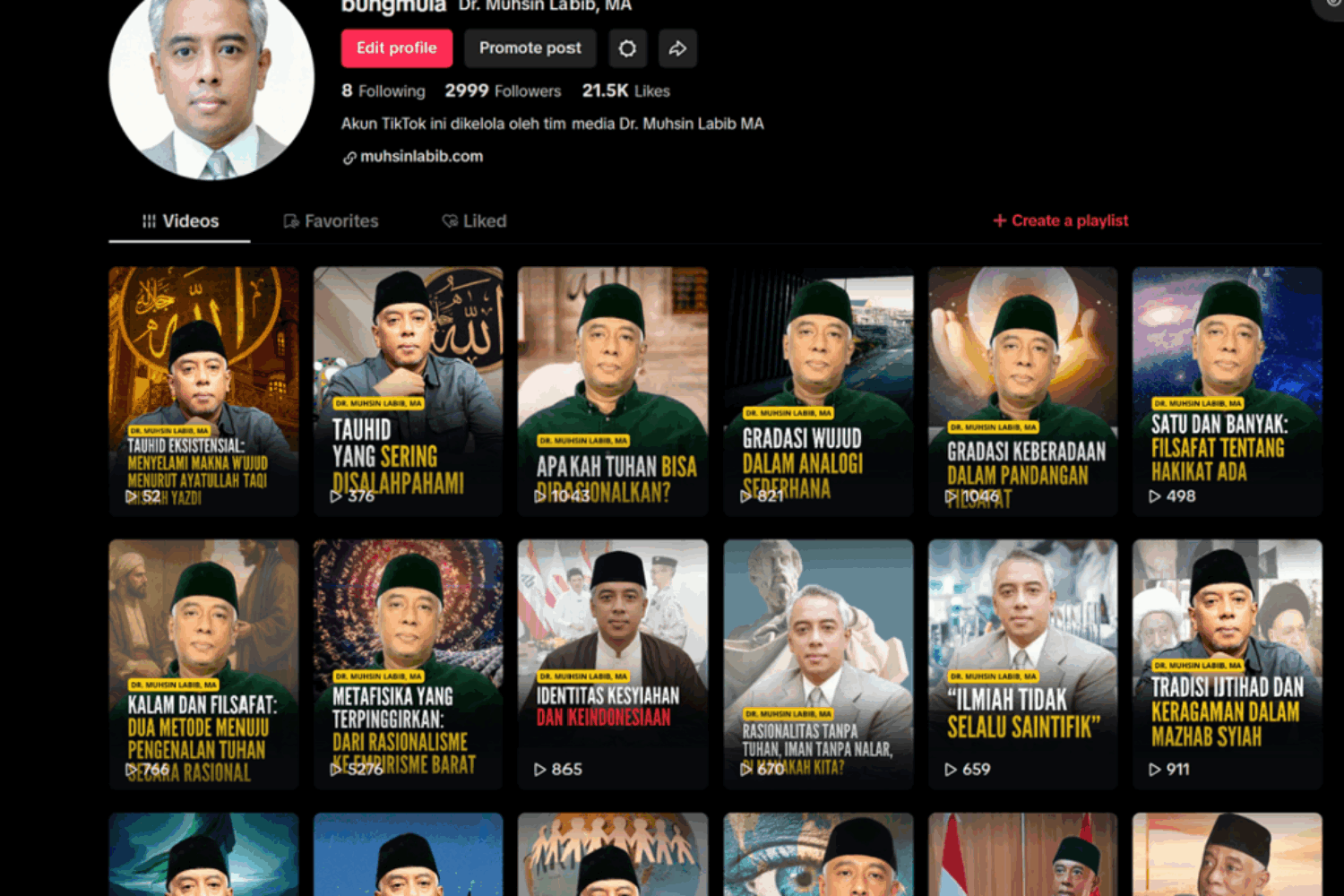Kemenangan Islam pasca-Fathu Makkah ternyata bukan akhir perlawanan. Di balik pengakuan lisan para tuan tanah Mekkah, saudagar budak, dan lingkaran oligarki Quraisy yang korup, mengendap dendam pekat bagai racun yang meresap perlahan. Mereka—yang kakinya terpelanting dari singgasana privilege—memandang Nabi SAW bukan sebagai pembawa hidayah, melainkan penakluk licik yang menggantikan animisme dengan rezim baru. Tauhid dianggap siasat, risalah langit dicurigai sebagai skenario kuasa.
Dendam itu menjelma dalam sikap dingin, bisik-bisik hasutan, dan penentangan sporadis. Lebih berbahaya: konspirasi gank bromocorah Quraisy ini merancang skenario rumit untuk menggagalkan proyeksi jangka panjang Sang Rasul—antisipasi cermat beliau agar revolusi tauhid tak dikhianati. Segala muslihat dijalankan demi melumpuhkan otoritas kenabian, terutama saat isyarat suksesi mulai beliau sampaikan.
Firman Allah mengkonfirmasi kegetiran ini: “Di antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik; dan (juga) di antara penduduk Madinah…”(QS. At-Taubah: 101). Mereka adalah gerombolan bermuka dua yang giat meracuni legitimasi Nabi.
Namun sejarah punya cara membongkar kepalsuan. Tragedi Asyura di Karbala menjadi saksi abadi. Di sini, wajah Jahiliah Baru tampak nyata: sebuah oligarki berjubah agama. Bani Umayyah— elit korup Quraisy yang berubah wujud jadi penguasa “Muslim”—menciptakan tirani berwajah syariat. Kekuasaan mereka adalah parodi atas risalah Nabi: syahwat duniawi yang menggerus ruh spiritual, keangkuhan feodal yang menginjak egalitarianisme Islam.
Maka Al-Husain bin Ali tegak menghadang. Keberangkatannya dari Madinah adalah perlawanan diam terhadap sistem jahiliah yang disokong circle oligarki itu. Dengan menanggalkan hak istimewa sebagai cucu Rasulullah, ia membuktikan: keluarga Nabi tidak diutus untuk menumpuk kuasa, tapi mengalirkan pengorbanan. Seruannya, “Bila agama kakekku menuntut tumbal, ambil nyawaku!” adalah palu godam yang merontokkan klaim gank bromocorah bahwa Islam dibangun untuk dinasti.
Di Karbala, Al-Husain membongkar topeng oligarki berjubah tauhid. Pembantaian keji atasnya beserta keluarga adalah bukti telak: ketika rezim mengorbankan cucu Rasulullah di altar kekuasaan, ia telah menelanjangi dirinya sebagai Jahiliah yang bersemi kembali.
Maka pekik “Pantang Hina!” yang menggema di padang Karbala adalah guruh penghancur bagi seluruh bangunan kebatilan. Darah syuhada itu menjadi api abadi yang membakar topeng elit munafik, menyinari setiap zaman di mana oligarki baru berusaha bangkit. Di sanalah Asyura berdiri tegak—sebagai benteng perlawanan abadi yang memastikan: kebenaran tak akan pernah dikubur dalam kubangan kehinaan.