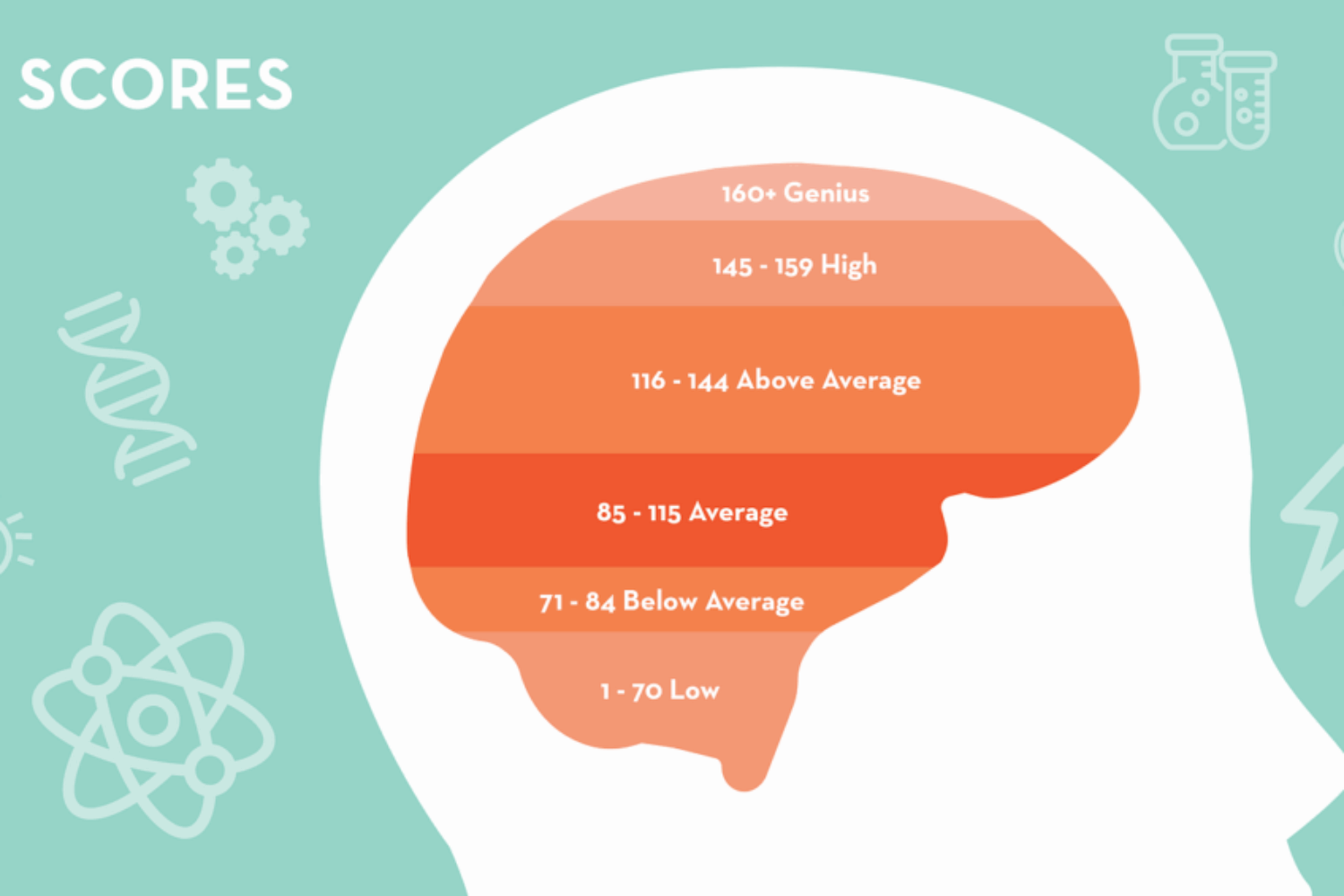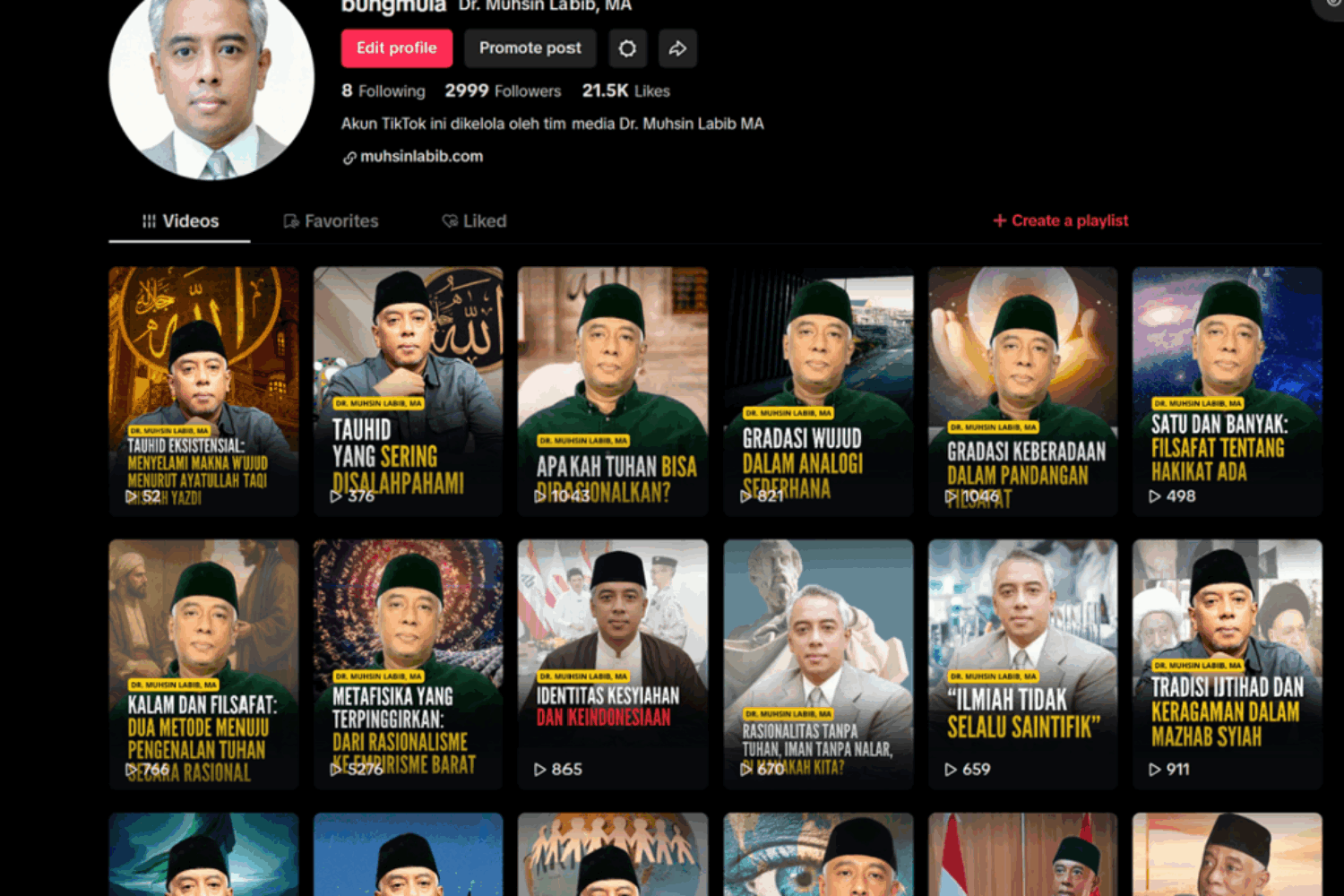Saya bukan pemimpin pesantren atau hawzah (sekolah keagamaan Islam Syiah), bukan pula perawat jamaah dalam majelis taklim, atau pengelola husainiyah—tempat untuk peringatan keagamaan dan doa bersama. Saya juga belum mendirikan yayasan atau lembaga keagamaan dengan tim pengurus. Hidup saya sederhana, sebagai pemikir ala kadarnya dan pembagi ilmu nomaden, seperti mantri keliling yang menyebarkan pengetahuan dengan semangat ringan. Ketika dipanggil untuk memberikan ceramah agama atau menjadi narasumber seminar, saya berpindah dari kota ke kota, membawa tas ransel atau tas kain kesayangan. Di dalamnya, hanya ada charger, obat-obatan, vitamin, sikat gigi, dan peralatan kebersihan secukupnya—sahabat setia yang menyaksikan langkah saya dari masjid kecil hingga ruang diskusi intelektual. Tas itu adalah saksi bisu perjalanan saya, membawa cerita dari satu tempat ke tempat lain.
Untuk menyiasati cap pengangguran, saya mengajar sebagai dosen honorer satu hari dalam seminggu, berbagi ilmu dengan mahasiswa yang penuh rasa ingin tahu. Di luar itu, saya sering berkumpul dengan teman-teman dekat—genk saya—di kafe outdoor Abi Mousa Condet, berbagi tawa dan ide di bawah lampu temaram. Namun, lebih sering, saya menyendiri di kafe seperti Point Indomaret atau Janji Jiwa di Jakarta Selatan. Di sana, saya menyelami dunia internet, mencari berita terkini tentang Iran, Palestina, Lebanon, atau kawasan Asia Barat, sambil menuangkan renungan tengah malam tentang politik, filsafat, atau momen kecil yang saya amati—seperti sapaan hangat pelayan kafe atau tawa anak kecil di trotoar.
Perjalanan ini tidak selalu mudah. Selama tiga puluh tahun, stigma “tokoh Syiah” melekat pada saya, membawa dampak nyata pada kehidupan material. Bersama stigma etnis yang lebih menyakitkan, label ini membatasi ruang gerak saya. Ide-ide tentang agama, mazhab, manusia, budaya, bangsa, filsafat dan lainnya yang saya pelajari dan kembangkan sulit menjangkau khalayak luas. Karier saya tersendat, kesempatan untuk berkontribusi bagi masyarakat terbatas, dan ketenangan diri serta keluarga sering terganggu. Banyak orang menjaga jarak, bukan karena siapa saya, tetapi karena label yang mereka sematkan.
Di tengah keterbatasan itu, saya mulai memimpikan langkah baru. Aset intelektual yang saya kumpulkan—catatan-catatan malam, renungan tentang kebenaran, dan pengalaman hidup—adalah harta yang ingin saya susun rapi. Saya membayangkan sebuah lembaga riset atau pendidikan, di mana tim berdedikasi dapat mengelola dan menyebarkan pengetahuan ini. Lembaga ini akan menjadi wadah untuk merangkum ide-ide saya tentang agama, mazhab, dan filsafat, menjadikannya lentera bagi mereka yang mencari pencerahan. Ini adalah cita-cita yang kini tumbuh, sebuah panggilan untuk memperluas dampak ilmu yang selama ini saya bagikan secara nomaden.
Saya belajar bersyukur, tidak hanya atas apa yang saya impikan, tetapi juga atas karunia yang tak pernah terpikirkan. Tuhan mengganti kepedihan itu dengan hadiah tak terduga: segelintir manusia yang hadir dengan ketulusan luar biasa. Mereka bukan keluarga, bukan terikat darah atau sejarah, tetapi mereka memilih saya sebagai saudara. Ada yang mengikrarkan ikatan itu dalam percakapan penuh makna, ada pula yang menunjukkannya lewat kehadiran mereka—dalam obrolan ringan di kafe, diskusi panjang tentang hidup, atau diam bersama di saat sulit. Mereka adalah oase di tengah gurun stigma dan keterbatasan, menebus luka yang saya simpan dalam diam.
Karunia tak terduga ini mengajarkan saya bahwa hidup, dengan segala tantangannya, selalu menyisakan ruang untuk keajaiban kecil. Mungkin, seperti saya, banyak orang di luar sana bergulat dengan stigma atau penolakan. Namun, di sela-sela itu, selalu ada harapan—dalam senyum tak terduga, pertemuan yang menghangatkan, atau ikatan yang tak direncanakan. Saya bersyukur atas tas kain yang setia, atas renungan malam yang penuh makna, dan atas saudara-saudara baru yang Tuhan kirimkan.
Lebih dari itu, saya bersyukur atas visi yang kini tumbuh di hati, mengundang saya—dan mungkin juga Anda—untuk melihat hidup dengan mata hati, menemukan anugerah di balik setiap kegetiran.