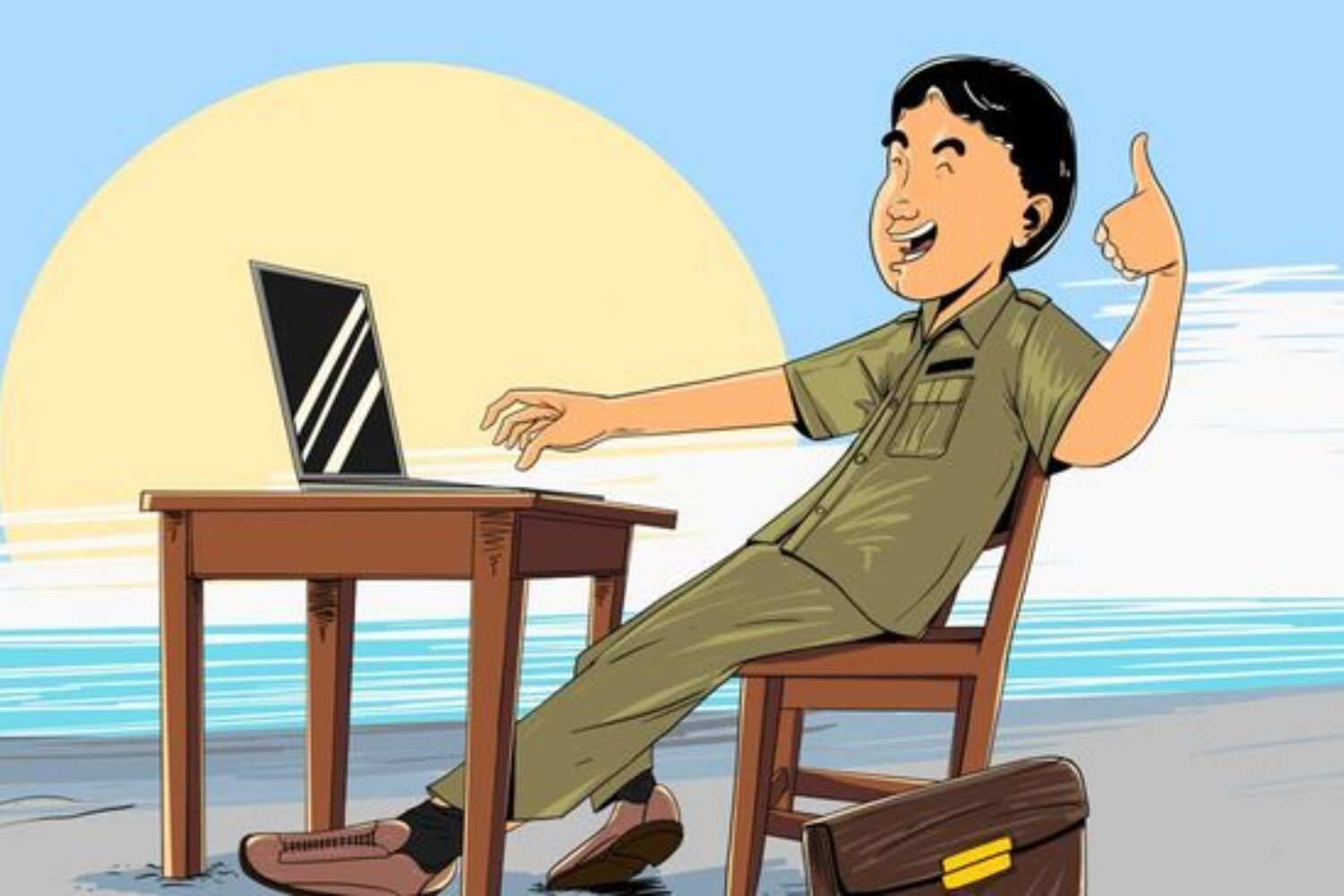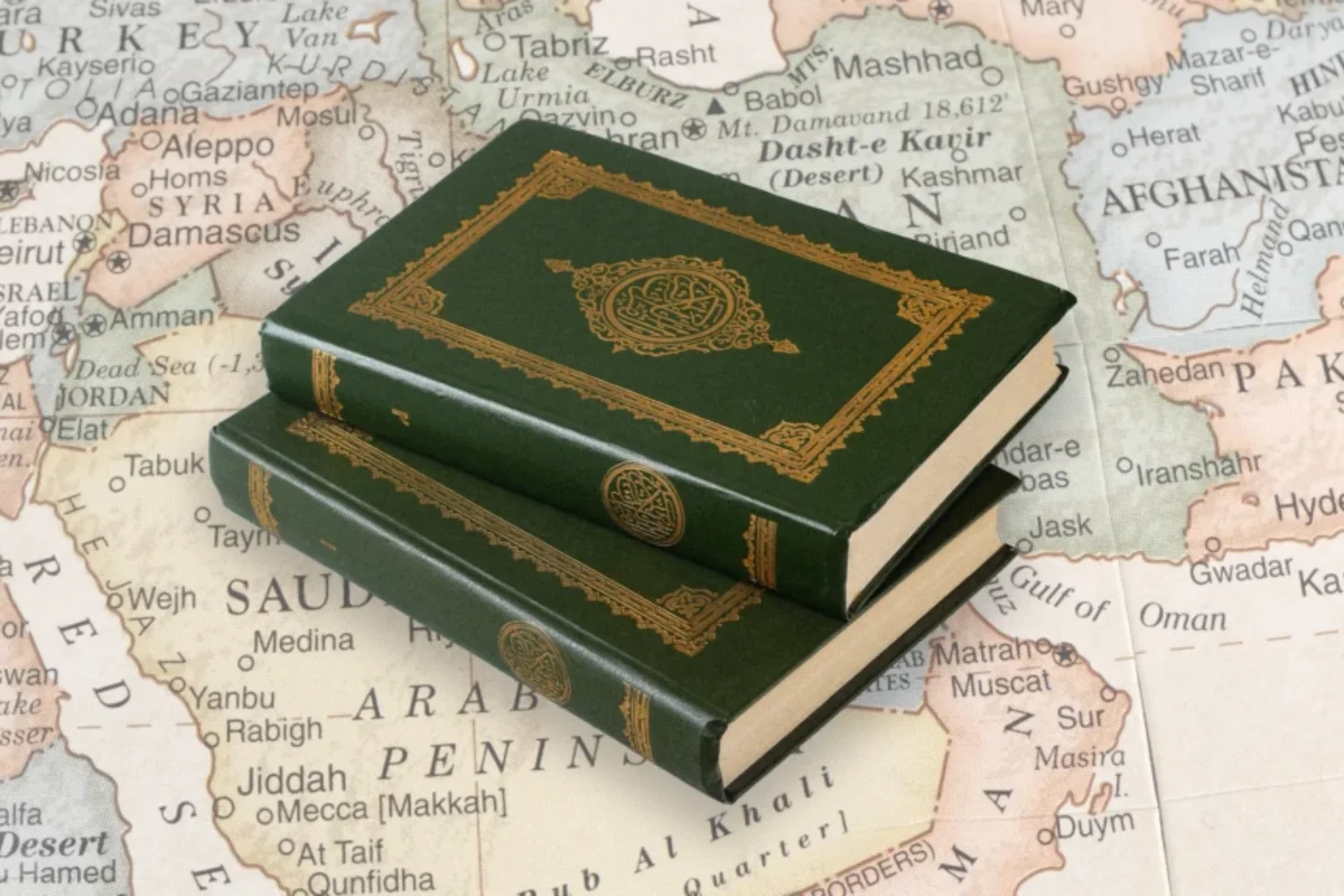Dalam arsitektur keagamaan kontemporer, ilmu agama yang semestinya membebaskan telah bertransformasi menjadi alat legitimasi bagi ‘rezim agamawan’. Berpusat di institusi pendidikan agama berasrama, rezim ini mengutamakan loyalitas pada figur pemegang otoritas ketimbang ajaran agama itu sendiri. Insiden runtuhnya bangunan dalam lingkungan lembaga pendidikan agama yang “otononom” bukan hanya tragedi fisik, melainkan metafora pahit dari kerapuhan kekuasaan yang dibangun di atas eksploitasi. Rezim ini memutarbalikkan esensi agama, menggantikan misi pembebasan dengan hierarki yang menindas, sering kali dengan memanfaatkan tenaga fisik pengikutnya untuk kepentingan institusi.
Agamawan seharusnya menjadi penyalur pengetahuan suci, namun rezim ini membangun menara gading yang memisahkan ‘yang berilmu’ dari ‘awam yang harus patuh’. Eksploitasi fisik kerap terjadi, di mana tenaga pengikut diperas dengan dalih pendidikan atau pengabdian.
Penyebab utama adalah longgarnya kriteria otoritas agama. Kompetensi keilmuan, integritas moral, dan komitmen pada keadilan seharusnya menjadi fondasi, tetapi realitas menunjukkan gelar keagamaan sering diperoleh melalui warisan, kedekatan dengan penguasa, atau retorika yang memikat massa.
Ketiadaan standar ketat melahirkan pemimpin agama yang lebih mahir dalam manipulasi psikologis daripada pemahaman mendalam. Karisma menggantikan kapasitas, popularitas mengalahkan integritas, dan jaringan kekuasaan lebih dihargai daripada kedalaman spiritual. Tanpa mekanisme akuntabilitas, seperti audit moral atau evaluasi kompetensi, rezim ini bebas bertindak tanpa pengawasan. Akibatnya, muncul tirani spiritual yang terselubung kesalehan, di mana otoritas agama menjadi alat untuk memperkuat kekuasaan pribadi.
Praktik di lembaga pendidikan agama sering mencerminkan logika korup rezim ini. Hukuman bagi pelanggar aturan bukanlah pendisiplinan edukatif, melainkan eksploitasi tenaga untuk kepentingan institusi, seperti pembangunan fisik. Praktik ini dibungkus dengan doktrin “khidmat” atau janji “berkah” yang akan mempermudah pemahaman ilmu. Hubungan spiritual dikomodifikasi, menjadikan kesetiaan dan tenaga sebagai mata uang untuk ‘membeli’ keberkahan, seolah-olah karunia ilahi dapat diukur dengan pengabdian fisik kepada pemimpin.
Lebih mengkhawatirkan, sistem ini menormalkan ketidakadilan. Alumni yang pernah mengalami eksploitasi serupa sering kali melanggengkan praktik tersebut, dengan logika “saya dulu juga begini”. Siklus viktimisasi ini memperkuat struktur penindasan yang disamarkan sebagai “tradisi mulia”. Generasi baru terjebak dalam pola yang sama, menganggap eksploitasi sebagai bagian wajar dari pendidikan agama, padahal ini hanyalah mekanisme reproduksi kekuasaan yang korup.
Rezim agamawan bertumpu pada tiga pilar. Pertama, monopoli akses ilahi dan epistemik, di mana ilmu dikemas sehingga keselamatan hanya diraih melalui ketaatan pada sistem mereka. Pengetahuan yang seharusnya terbuka dibuat seolah rahasia yang hanya bisa diakses melalui elite agama, menciptakan ketergantungan. Kedua, birokrasi ibadah dan khidmat, yang menstandarisasi pemikiran dan menjadikan kerja fisik paksa sebagai ukuran kesalehan. Kepatuhan buta dianggap “adab”, sementara kritik dipandang sebagai pembangkangan, melemahkan otonomi intelektual individu. Ketiga, kultus individu dan mistifikasi figur, di mana pemegang otoritas agama menjadi ‘majikan spiritual’ dengan aura kesucian buatan. Loyalitas buta dianggap bukti ketakwaan, didukung oleh narasi keajaiban atau silsilah spiritual yang dimuliakan. Kritik terhadap orang yang memegang otoritas agama dianggap penghianatan, menciptakan ketergantungan emosional dan isolasi dari sumber pengetahuan alternatif.
Agama sejati mengajarkan keadilan dan kemerdekaan, namun rezim ini membangun kekuasaan atas penindasan. Keruntuhan fisik di lembaga agama harus menjadi momen introspeksi: apakah fondasi kita dibangun atas keadilan atau eksploitasi? Ketaatan sejati adalah pada nilai-nilai luhur, bukan ambisi duniawi figur yang menindas atas nama agama.