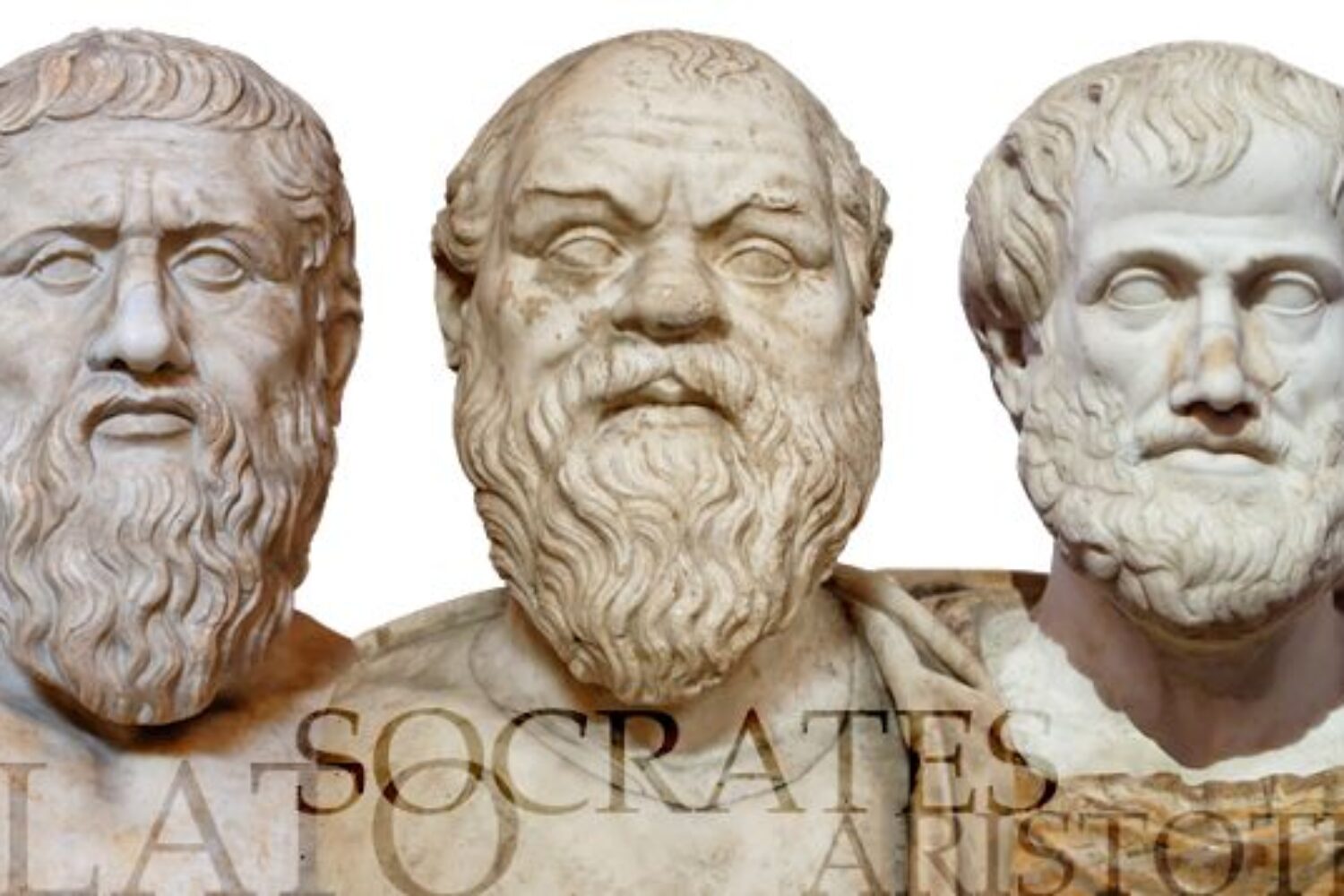Di panggung kuliner modern, kita disuguhi sebuah opera tragikomedi yang absurd. Di satu sisi, berdiri megah kuil-kuil gastronomi berbalut estetika Instagramable—restoran ala Barat, Jepang, atau Korea dengan interior minimalis yang seolah dirancang oleh algoritma Pinterest. Lampu temaramnya memaksa Anda menyipitkan mata untuk membaca menu, yang lebih mirip puisi modernis daripada daftar makanan. Di sisi lain, dengan gagah berani bertahan warung tegal (warteg), kuil rakyat dengan display kaca bening yang lebih jujur daripada janji politisi. Dua dunia ini bukan sekadar soal selera, melainkan pertempuran filsafat: distrust yang dibungkus teknologi canggih versus trust yang sederhana namun menghantam seperti sambal ulek yang dibuat dengan cinta.
Masuklah ke restoran “kekinian” yang harganya cukup untuk membiayai pendidikan anak tetangga. Anda disambut bukan oleh senyum manusiawi, melainkan oleh tablet touchscreen yang lebih dingin daripada ekspresi kasir di minimarket. Langkah pertama? Mengantri untuk mendapat “kehormatan” membelanjakan gaji sebulan. Setelah berhasil melewati ujian kesabaran itu, Anda disodori menu dengan istilah-istilah seperti “deconstructed quinoa,” “umami explosion,” atau “nitrogen-infused foam”—seolah Anda sedang mendaftar kelas masterchef, bukan sekadar ingin mengisi perut. Belum sempat mencium aroma makanan, Anda sudah dihadapkan pada hukum besi: bayar di muka! Sistem ini berteriak, “Kami tidak percaya Anda cukup kaya untuk membayar setelah makan!” atau “Kami khawatir Anda kabur begitu tahu harga segenggam truffle itu lebih mahal dari motor Anda!” Ini adalah dunia distrust yang dikemas dalam font sans-serif dan interior serba abu-abu. Setiap langkah dirancang untuk mengingatkan Anda: “Kami tidak percaya Anda, tapi silakan nikmati microgreens kami.”
Sekarang, bandingkan dengan pengalaman warteg yang seperti pelukan hangat dari nenek. Filosofinya? Trust, dengan huruf kapital T. Tidak ada antrean bak ujian masuk universitas, tidak ada tablet yang membuat Anda merasa buta huruf teknologi. Anda cukup melangkah ke kaca pajangan—galeri seni kuliner yang jujur—dan dengan keajaiban jari telunjuk, Anda “memprogram” pesanan: “Bang, yang ini, itu, sama itu yang merah-merah.” Tidak ada kontrak, tidak ada deposit, tidak ada sidik jari sebagai jaminan. Anda dianggap tamu terhormat, bukan tersangka dalam drama kriminal kuliner. Anda makan sepuasnya, menikmati simfoni nasi hangat, sayur kolplay, dan ayam goreng yang lebih reliable daripada koneksi Wi-Fi restoran fancy. Baru setelah kenyang, Anda mendekati sang pemilik dengan kalimat sakral, “Berapa, Bang?” Dengan kecepatan kalkulator manusia, Bang menghitung—kadang sambil nyanyi dangdut pelan—dan transaksi selesai dengan senyum. Ini bukan sekadar makan; ini adalah ritual kepercayaan yang lebih suci daripada janji manis di aplikasi kencan.
Ironinya, restoran mahal yang mengklaim sebagai puncak peradaban justru memperlakukan pelanggan seperti penutup dompet yang berpotensi kabur. Mereka menyebutnya “kemajuan,” tapi kemajuan apa yang mengharuskan Anda menandatangani perjanjian sebelum menyesap kopi artisan? Sementara warteg, yang sering dicap “kampungan” oleh para foodie berfilter Instagram, justru menawarkan pelajaran kemanusiaan tingkat dewa: kepercayaan tanpa syarat. Di warteg, nilai Anda tidak diukur dari limit kartu kredit atau jumlah followers, tapi dari kemampuan Anda untuk berkata jujur, “Bang, tadi saya ambil telur dua.”
Restoran fancy mungkin mahal karena mereka harus membayar “asuransi ketidakpercayaan”: sistem POS yang harganya setara mobil bekas, aplikasi manajemen pelanggan yang lebih rumit daripada skripsi, dan pelayan yang diam-diam dilatih untuk mengawasi tamu seperti detektif swasta. Warteg? Biaya operasionalnya rendah karena sistem keamanannya adalah hati nurani dan tatapan tajam Buah Hati, istri sang pemilik, yang tahu persis kalau Anda coba-coba “lupa” bayar tempe.
Satire yang lebih pahit dari kopi decaf: kita rela membayar ratusan ribu untuk merasakan ketidakpercayaan, tapi kepercayaan sejati justru kita temukan di tempat yang harganya tak sampai menguras dompet.
Pada akhirnya, memilih antara restoran distrust dan warteg trust bukan cuma soal perut, tapi soal jiwa. Apakah Anda ingin dunia yang penuh prosedur, kode QR, dan kecurigaan yang dibungkus estetika? Atau dunia di mana sepiring nasi, sepotong ayam, dan segelas es teh bisa menyelesaikan semua keraguan dengan modal saling percaya? Jadi, silakan sentuh kaca warteg itu, pilih lauk Anda, dan buktikan bahwa trust adalah bumbu paling langka—yang tak bisa dibeli dengan truffle oil sekalipun. Makanlah, lalu bayar dengan jujur. Karena di dunia ini, kepercayaan adalah menu termahal yang selalu gratis di warteg.