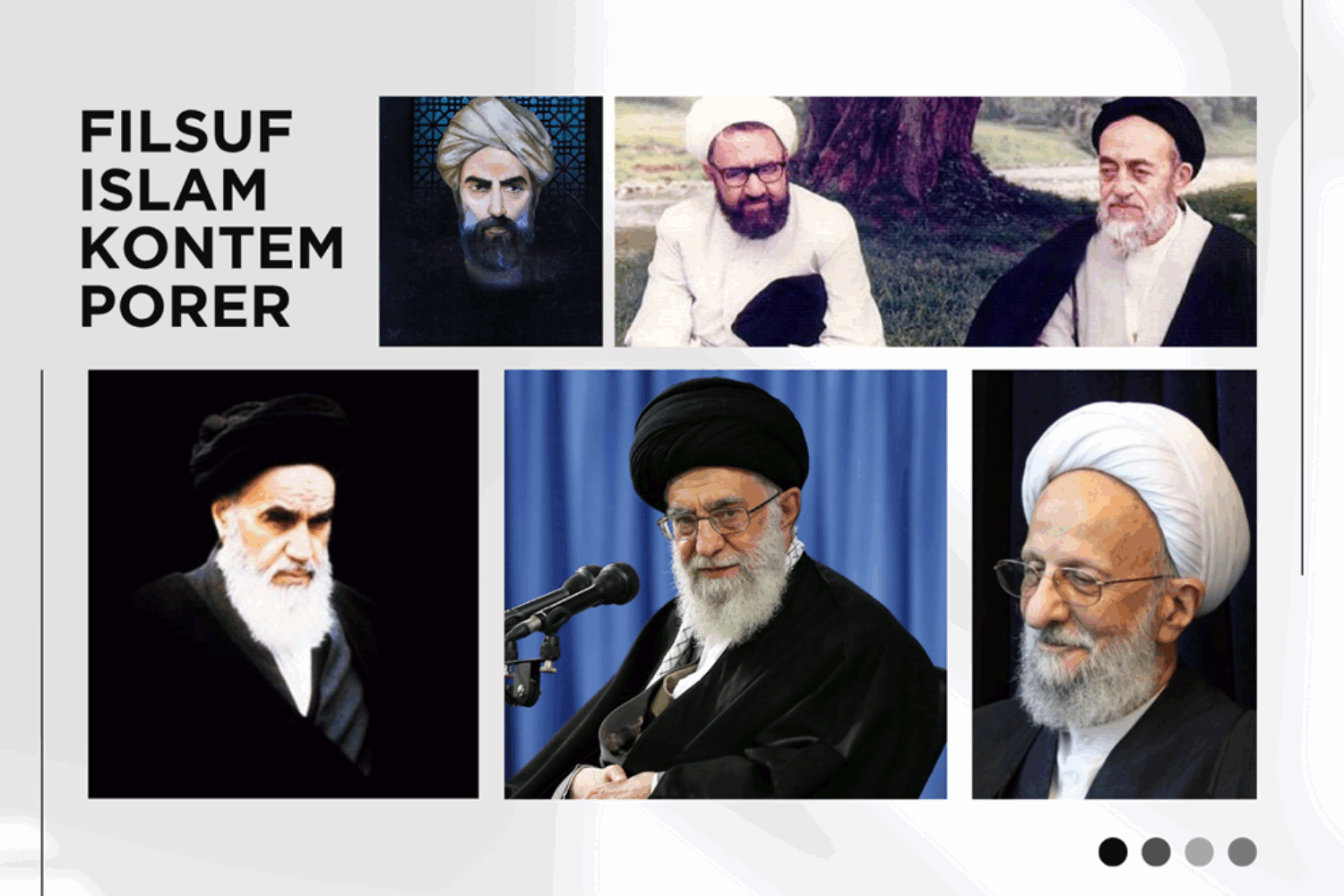Sejarah filsafat setua peradaban manusia itu sendiri. Manusia berbeda dari makhluk lain bukan hanya melalui kemampuan makan dan berkembang biak, tetapi melalui kapasitas berpikir dan bertindak berdasarkan pemikiran mendalam. Sejak awal keberadaannya, pemikiran telah menjadi esensi eksistensi manusia. Namun, seiring waktu, banyak individu bertindak bukan atas dasar akal sehat, melainkan didorong kepentingan pribadi dan kelompok. Akibatnya, berpikir secara mendalam menjadi langka, bahkan dianggap aneh oleh sebagian masyarakat.
Lambat laun, kepentingan individu dan komunal mendominasi, menggeser logika yang sering bertentangan dengan keuntungan sementara. Kondisi ini mendorong sekelompok individu waras dan jujur untuk menentang arus pemikiran dangkal yang subjektif. Mereka menamai gerakan intelektual mereka philosophia—istilah Yunani yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai filsafat. Berasal dari philos (cinta) dan sophia (kebijaksanaan), filsafat secara harfiah berarti “cinta akan kebijaksanaan.” Konsep ini dipopulerkan oleh Plato, yang menyebut gurunya, Socrates, sebagai philosophos—pencinta kebijaksanaan sejati.
Dalam dunia Arab dan Islam, istilah ini diadaptasi menjadi falsafah, merujuk pada pencarian kebenaran oleh para pemikir. Sebelum Socrates, ada kelompok yang menyebut diri sophist (cendekiawan), yang memandang persepsi manusia sebagai ukuran realitas. Namun, mereka sering menggunakan argumen menyesatkan, sehingga kata sophist menjadi pejoratif, merujuk pada manipulasi logika—dikenal sebagai sophistry dalam bahasa Inggris atau safsathah dalam bahasa Arab. Karena kerendahan hati dan keinginan menjauhkan diri dari konotasi negatif ini, Socrates memilih philosophos, menandakan ia bukan pemilik kebijaksanaan, melainkan pencarinya.
Filsafat didefinisikan beragam oleh para pemikir. John Dewey melihatnya sebagai hubungan antara pengajaran dan pendidikan, sementara Bertrand Russell dan ahli matematika lain menawarkan pandangan unik. Alfred North Whitehead mendefinisikan filsafat sebagai “perlawanan ruh terhadap keyakinan-keyakinan yang diterima karena kebodohan,” menegaskan filsafat sebagai penolakan terhadap pemikiran tidak teruji dan tradisi yang tidak dipertanyakan.
Dalam Islam, konsep sophia, filsafat, metafisika, dan hikmah diadaptasi dan diperkaya melalui interaksi pemikiran Yunani dengan ajaran Al-Qur’an dan Hadis. Proses ini dimulai pada abad ke-8 Masehi di era Abbasiyah, ketika karya Aristoteles, Plato, dan filsuf Yunani lainnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab melalui Bayt al-Hikmah di Baghdad. Pemikir Muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina (Avicenna), Ibn Rushd (Averroes), Suhrawardi, dan Mulla Sadra mengintegrasikan warisan ini dengan prinsip tauhid dan wahyu, menciptakan tradisi filsafat Islam yang khas.
Sophia dalam Islam: Hikmah sebagai Kebijaksanaan Ilahiah Sophia, yang berarti “kebijaksanaan” dalam bahasa Yunani, diterjemahkan dalam Islam sebagai hikmah, tetapi dengan makna yang lebih dalam. Hikmah bukan sekadar pengetahuan intelektual, melainkan kebijaksanaan ilahiah yang bersumber dari Allah SWT dan terkait wahyu. Al-Qur’an menyebut hikmah sebagai karunia Tuhan kepada para nabi, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 269: “Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barangsiapa yang diberi hikmah, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak.” Hikmah mencakup pemahaman kebenaran hakiki, etika, dan tindakan yang selaras dengan kehendak Tuhan, melampaui spekulasi rasional.
Dalam filsafat Islam, hikmah berbeda dari pengetahuan biasa (‘ilm); ia adalah kebijaksanaan transenden yang melibatkan pemurnian jiwa (tazkiyah al-nafs) dan pencapaian ma’rifah (pengetahuan intuitif tentang Tuhan). Suhrawardi, pendiri mazhab iluminasionis (hikmat al-ishraq), menggabungkan sophia dengan mistisisme Islam, memandang hikmah sebagai “cahaya” (ishraq) yang menerangi akal untuk memahami realitas metafisik. Berbeda dengan sophist Yunani yang subjektif, hikmah Islam dibatasi syariat untuk mencegah kesesatan.
Filsafat dalam Islam: Falsafah sebagai Pencarian Kebenaran yang Terintegrasi
Filsafat, atau falsafah, diadaptasi sebagai “cinta akan hikmah” yang terintegrasi dengan Islam. Bukan pemikiran spekulatif semata, falsafah adalah disiplin yang mencari kebenaran melalui akal (‘aql) sambil tunduk pada wahyu (naql). Al-Farabi, dikenal sebagai “Guru Kedua” setelah Aristoteles, mendefinisikan falsafah sebagai “pengetahuan tentang segala yang ada sebagaimana adanya,” mencakup logika, etika, dan metafisika, tetapi harus selaras dengan ajaran Islam. Ia membedakan falsafah dari safsatah (sophistry) dengan menekankan pencarian objektif. Istilah hikmah sering digunakan bergantian dengan falsafah, terutama oleh Mulla Sadra dalam al-hikmat al-muta‘aliyah (kebijaksanaan transenden), yang mengintegrasikan akal, wahyu, dan intuisi.
Falsafah Islam berkembang menjadi kalam (teologi rasional) dan irfan (gnosis mistik), di mana akal dan wahyu saling melengkapi. Definisi Whitehead tentang filsafat sebagai penolakan keyakinan bodoh selaras dengan pandangan Islam, di mana falsafah adalah jihad intelektual melawan bid’ah dan taqlid buta.
Metafisika dalam Islam: ‘Ilm al-Ilahi sebagai Pengetahuan tentang Realitas Hakiki
Metafisika, berasal dari “meta ta physika” (setelah fisika) dalam tradisi Aristoteles, dikenal dalam Islam sebagai ‘ilm al-ma ba‘d al-tabi‘ah atau ‘ilm al-ilahi (pengetahuan tentang yang ilahi). Istilah ini berasal dari klasifikasi Andronikos dari Rhodi terhadap karya Aristoteles, yang menempatkannya setelah buku fisika. Bagi Yunani kuno, fisis merujuk pada dunia indrawi yang tunduk pada proses “menjadi,” sehingga metafisika membahas realitas tak terinderai, tidak berubah, dan rohaniah.
Dalam Islam, metafisika mengeksplorasi wujud (eksistensi), sebab-sebab pertama, dan sifat Tuhan. Ibn Sina, dalam Al-Shifa’, membagi metafisika menjadi ontologi, teologi, dan pengetahuan universal, dengan Tuhan sebagai Wajib al-Wujud (Yang Wajib Ada). Bagi Al-Farabi dan Ibn Arabi, realitas metafisik seperti alam malakut dapat dipahami melalui akal dan intuisi yang dibimbing wahyu. Suhrawardi, melalui hikmat al-ishraq, menggabungkan metafisika dengan mistisisme, menuju konsep wahdat al-wujud (kesatuan wujud). Berbeda dengan pandangan Nicolai Hartmann bahwa metafisika melampaui indra tetapi dapat diketahui, metafisikawan Muslim seperti Ibn Sina memandang realitas metafisik lebih nyata daripada dunia fisik, karena ia adalah dasar eksistensi.
Hikmah sebagai Sintesis: Kebijaksanaan Holistik dalam Islam
Hikmah adalah istilah sentral yang mencakup sophia, filsafat, dan metafisika dalam Islam. Berasal dari akar “h-k-m” (memutuskan benar), hikmah merujuk pada kemampuan menerapkan pengetahuan secara bijak, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an, seperti Surah Ali Imran ayat 164, di mana Nabi Muhammad SAW diberi kitab dan hikmah untuk membersihkan umat. Hikmah melampaui falsafah karena mengintegrasikan akal, hati (qalb), dan roh (ruh). Mulla Sadra, dalam Asfar al-Arba‘ah (Empat Perjalanan), memandang hikmah sebagai perjalanan jiwa dari dunia fisik ke metafisik. Bagi Sufi seperti Rumi, hikmah adalah “pengetahuan hidup” yang mendorong tindakan saleh, menjadi antidot terhadap pemikiran dangkal. Hikmah menolak kepentingan duniawi, mengarahkan manusia pada kebenaran Ilahi.
Dengan demikian, dari warisan Yunani hingga sintesis dalam Islam, sophia, filsafat, metafisika, dan hikmah mencerminkan pencarian abadi akan kebijaksanaan. Dalam Islam, pencarian ini menjadi ibadah, di mana akal dan wahyu bersatu untuk memahami realitas hakiki, membimbing manusia menuju kedekatan dengan Tuhan.