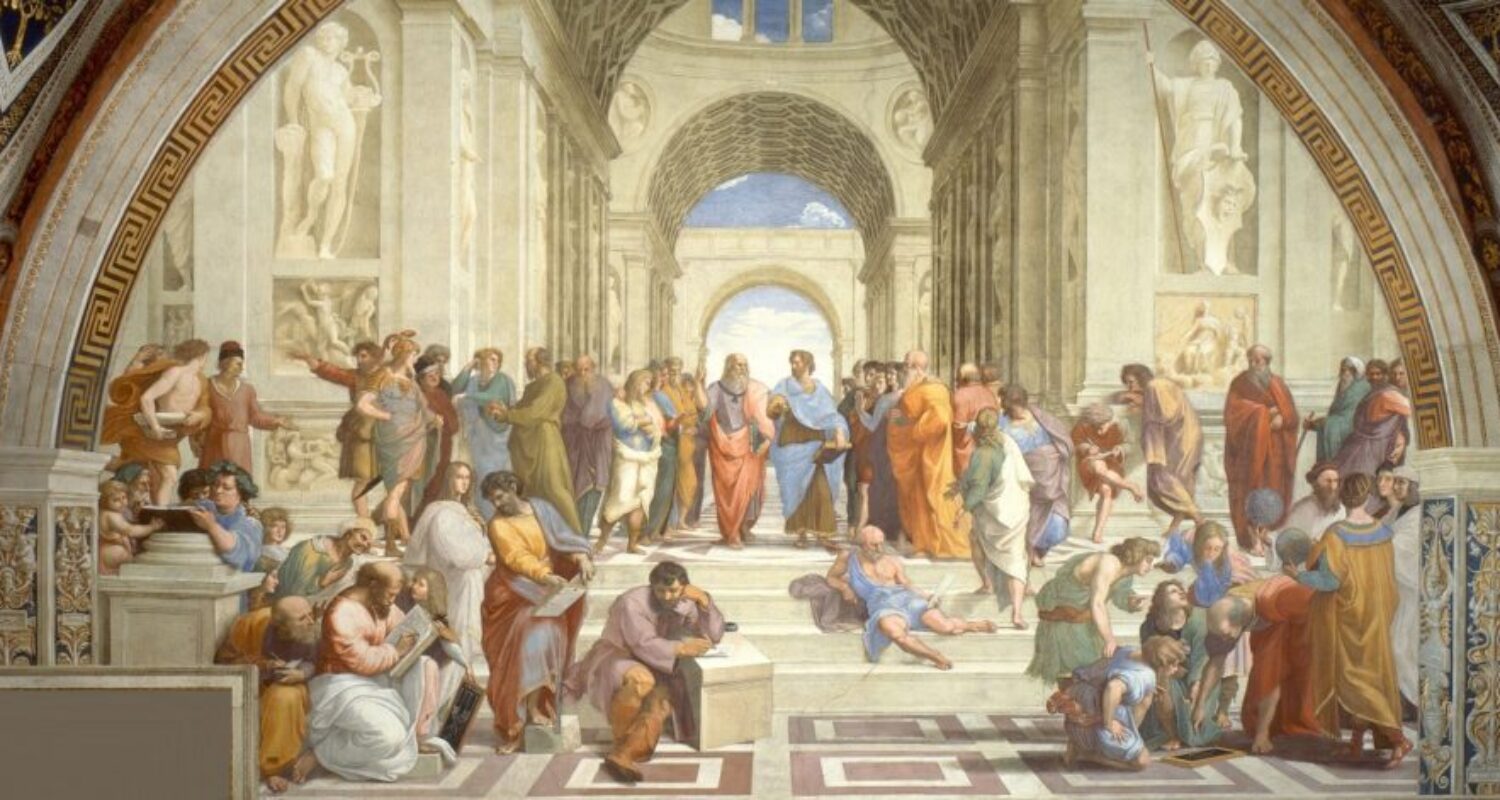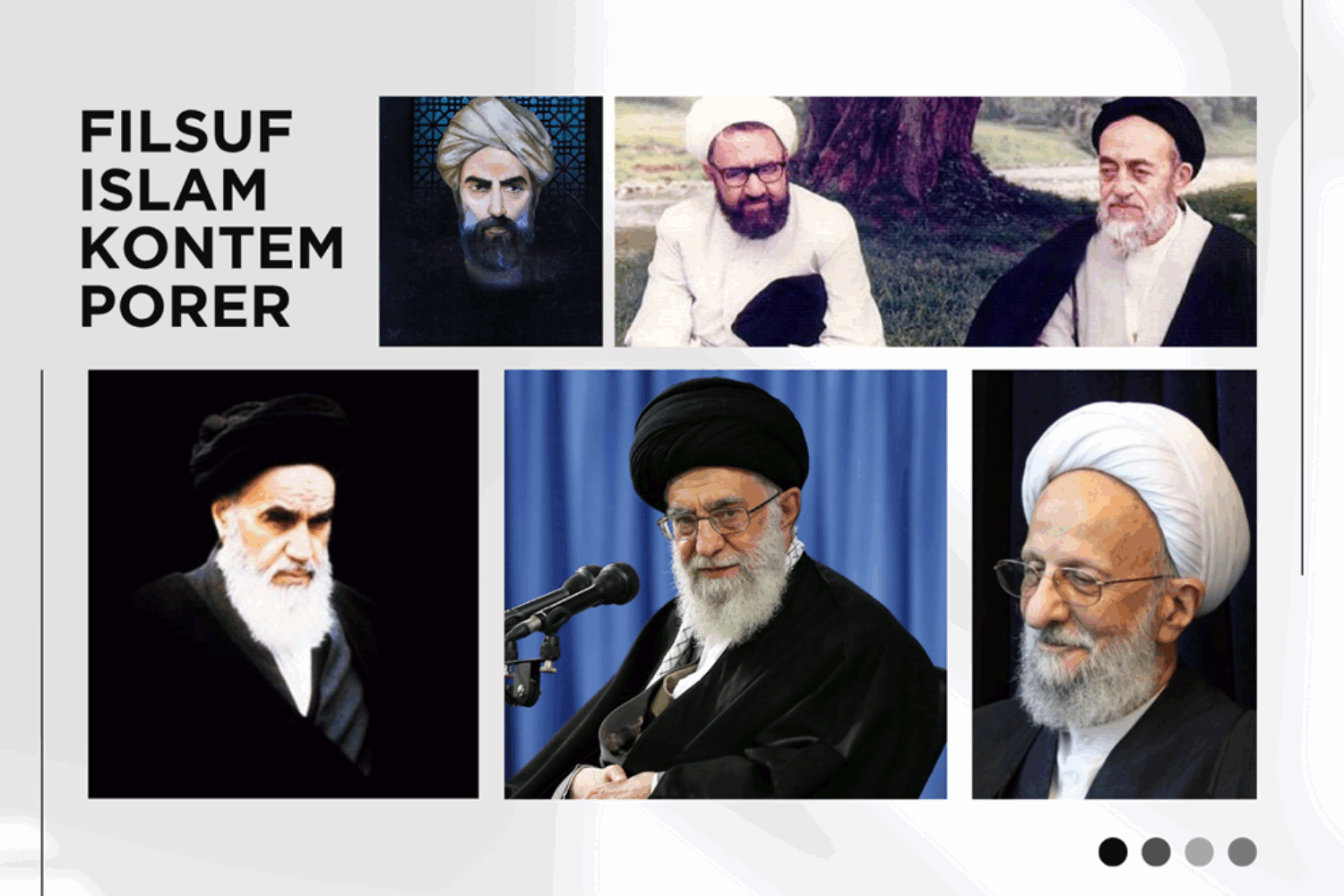ANTARA REALITAS DAN PIKIRAN, ANTARA PIKIRAN DAN REALITAS DAN ANTARA PIKIRAN DAN PIKIRAN
Dalam ontologi klasif khususnya yang dikembangkan oleh para filsuf Muslim, konsep-konsep universal dibagi menjadi tiga lapisan berdasarkan cara pembentukannya dan sifat dasarnya. Pemahaman tentang ketiga jenis konsep ini memberikan kerangka sistematis untuk memahami bagaimana pikiran manusia membangun pengetahuan dari pengalaman sederhana hingga refleksi filosofis yang mendalam.
Konsep primer merupakan fondasi paling dasar dari struktur pengetahuan manusia. Seperti batu pertama yang diletakkan dalam membangun sebuah gedung, konsep ini terbentuk langsung melalui persentuhan indra dengan dunia nyata. Ketika seseorang berulang kali melihat air dalam berbagai manifestasinya—mengalir di sungai, tertampung dalam gelas, atau turun sebagai hujan—akalnya secara alami mengekstrak esensi universal tentang “air”. Proses yang sama terjadi ketika mengamati individu-individu manusia seperti Agus, Budi dan orang-orang lain, yang kemudian melahirkan konsep umum tentang “manusia”. Demikian pula ketika menjumpai berbagai buku, baik buku filsafat, fikih, maupun mushaf Al-Qur’an, pikiran menyimpulkan konsep universal “buku”. Ciri khas konsep primer terletak pada kesederhanaannya yang menawan: pembentukannya tidak memerlukan perantara konsep lain, melainkan langsung dari pengalaman indrawi yang menjawab pertanyaan mendasar tentang hakikat sesuatu.
Pada tingkat yang lebih kompleks, konsep sekunder filsafat muncul sebagai hasil analisis mendalam terhadap hubungan-hubungan yang tersembunyi di balik fenomena. Konsep ini tidak lagi dapat ditangkap melalui pengamatan sederhana, melainkan membutuhkan kerja rasional yang lebih canggih. Ketika akal merenungkan fenomena “manusia diciptakan Tuhan”, ia tidak hanya melihat fakta tersebut, tetapi mengekstrak konsep yang lebih abstrak tentang “sebab-akibat”. Dari pengamatan “api membakar kayu”, lahir pemahaman tentang “kemungkinan” dan “keniscayaan”. Dari sifat “manusia yang fana”, terbentuk konsep “kebaruan”. Konsep-konsep ini menggambarkan struktur fundamental realitas, meskipun proses pemahamannya memerlukan langkah penalaran yang tidak langsung. Mereka berfungsi sebagai jembatan antara dunia konkret dan dunia ide, menghubungkan pengalaman fisik dengan refleksi metafisik.
Sementara itu, konsep sekunder logika beroperasi dalam wilayah yang sepenuhnya berbeda. Jika dua jenis konsep sebelumnya masih memiliki akar dalam realitas eksternal, konsep ini murni merupakan produk aktivitas akal yang menganalisis struktur konsep itu sendiri. Ketika pikiran merefleksikan konsep “manusia”, ia mengenali sifatnya sebagai “universal”—sebuah pengakuan yang tidak merujuk pada sifat fisik manusia di dunia, melainkan pada cara pikiran mengkategorikan gagasan. Ketika membandingkan konsep “manusia” dengan “hewan”, lahirlah pemahaman tentang “genus” dan “spesies”. Dari relasi “manusia memiliki akal”, muncul konsep “properti esensial”. Konsep-konsep ini sepenuhnya berada dalam ranah pemikiran, terlepas dari rujukan langsung pada realitas eksternal.
Penamaan “primer” dan “sekunder” dalam klasifikasi ini bukanlah sekadar konvensi terminologis, melainkan mencerminkan urutan logis dan ontologis dalam pembentukan pengetahuan. Konsep primer mendapat nama demikian karena mewakili lapisan pertama dan paling fundamental dari pengetahuan manusia. Ia bagaikan fondasi bangunan yang langsung bersentuhan dengan tanah realitas, di mana proses dimulai dari indra yang menangkap benda-benda konkret, lalu akal mengabstraksikannya menjadi konsep universal. Tanpa lapisan primer ini, mustahil bagi pikiran untuk membangun struktur pengetahuan yang lebih kompleks.
Konsep sekunder, baik filsafat maupun logika, dinamai demikian karena pembentukannya memerlukan perantara konsep primer. Mereka seperti lantai kedua dan ketiga pada bangunan yang membutuhkan fondasi kokoh terlebih dahulu.
Tanpa adanya konsep dasar seperti “manusia”, mustahil memahami konsep turunan seperti “manusia adalah spesies” atau “manusia adalah akibat dari sebab pertama”. Hubungan ketergantungan ini menunjukkan hierarki epistemologis yang tidak dapat dibalik.
Perbedaan mendasar antara ketiga jenis konsep ini terletak pada cara mereka berhubungan dengan realitas dan pikiran. Dalam konsep primer, sifat-sifat yang terkandung di dalamnya secara nyata melekat pada benda-benda di dunia fisik. Ketika kita menyatakan “Agus adalah manusia”, sifat kemanusiaan benar-benar ada pada diri Agus sebagai entitas fisik yang dapat diindrai. Pembentukan konsep ini bersifat langsung dan tidak memerlukan mediasi konseptual yang rumit.
Sebaliknya, dalam konsep sekunder logika, sifat-sifatnya hanya eksis dalam konstruksi pikiran. Pernyataan “Manusia adalah universal” tidak menggambarkan sifat fisik manusia yang berjalan di jalanan, melainkan cara pikiran mengkategorikan dan mengorganisasi gagasan. Proses pembentukannya murni melalui refleksi akal atas konsep yang sudah ada, tanpa rujukan langsung pada pengalaman indrawi.
Konsep sekunder filsafat menempati posisi unik di antara keduanya. Sifat-sifatnya memang melekat pada realitas eksternal, tetapi pengenalan terhadapnya memerlukan analisis mental yang mendalam. Ketika kita mengatakan “Api adalah sebab kebakaran”, hubungan kausal itu benar-benar nyata di dunia fisik. Api memang memiliki kekuatan untuk membakar, dan kebakaran memang merupakan akibat dari kehadiran api. Namun, pemahaman tentang hubungan sebab-akibat itu sendiri membutuhkan kerja rasional yang tidak sederhana. Konsep ini menjembatani dunia konkret dan abstrak, menghubungkan pengalaman fisik dengan refleksi filosofis.
Untuk memberikan ilustrasi yang lebih konkret, bayangkan pengalaman tentang batu. Ketika seseorang menyentuh batu kali, pengalaman indrawi langsung ini menghasilkan konsep primer “batu”. Sifat kebatuan—kekerasan, kepadatan, tekstur—secara nyata melekat pada objek fisik tersebut. Tidak ada mediasi konseptual yang diperlukan; pikiran langsung menangkap esensi universalnya dari pengalaman particular.
Namun, ketika orang tersebut mengamati bahwa batu yang dilempar dapat memecahkan kaca jendela, pengalaman ini melahirkan konsep sekunder filsafat tentang “sebab”. Sifat sebagai penyebab memang nyata—batu benar-benar memiliki kemampuan kausal untuk memecahkan kaca. Tetapi pemahaman tentang hubungan sebab-akibat ini memerlukan analisis rasional yang melampaui pengalaman indrawi sederhana.
Sementara itu, ketika pikiran merenungkan konsep “batu” itu sendiri dan menyadari bahwa ia merujuk pada entitas particular (bukan universal seperti konsep “kemanusiaan”), lahirlah konsep sekunder logika “batu adalah partikular”. Sifat partikularitas ini tidak melekat pada batu fisik di dunia, melainkan merupakan cara pikiran mengkategorikan jenis konsep tersebut dalam struktur logis.
Penggunaan istilah “konsep intelektual” untuk menggambarkan ketiganya menekankan bahwa semuanya merupakan produk aktivitas akal manusia, meskipun dengan cara dan tingkat yang berbeda. Pembagian tripartit ini menunjukkan peta jalan epistemologis yang lengkap: dimulai dari pengenalan terhadap benda-benda konkret melalui indra, berlanjut pada pemahaman hubungan dan struktur yang tersembunyi dalam realitas, dan bermuara pada kesadaran reflektif tentang cara kerja pikiran itu sendiri.
Setiap lapisan dalam hierarki ini membangun landasan untuk lapisan berikutnya, membentuk piramida pengetahuan yang utuh dan sistematis. Konsep primer menyediakan material mentah, konsep sekunder filsafat mengungkap pola dan hubungan, sementara konsep sekunder logika memungkinkan kesadaran diri epistemologis. Tanpa salah satu dari ketiga elemen ini, struktur pengetahuan manusia akan timpang dan tidak sempurna. Dalam konteks yang lebih luas, klasifikasi ini mencerminkan kekayaan dan kompleksitas pikiran manusia dalam membangun pemahaman tentang dunia.
Dari pengalaman sederhana menyentuh air hingga refleksi mendalam tentang sebab-akibat dan universalitas, akal manusia menunjukkan kemampuannya yang luar biasa untuk tidak hanya mengenali realitas, tetapi juga memahami cara kerjanya sendiri dalam proses pengenalan tersebut. Inilah yang menjadikan tradisi intelektual Islam begitu kaya dan mendalam, karena tidak hanya memahami dunia, tetapi juga memahami cara memahami dunia itu sendiri.