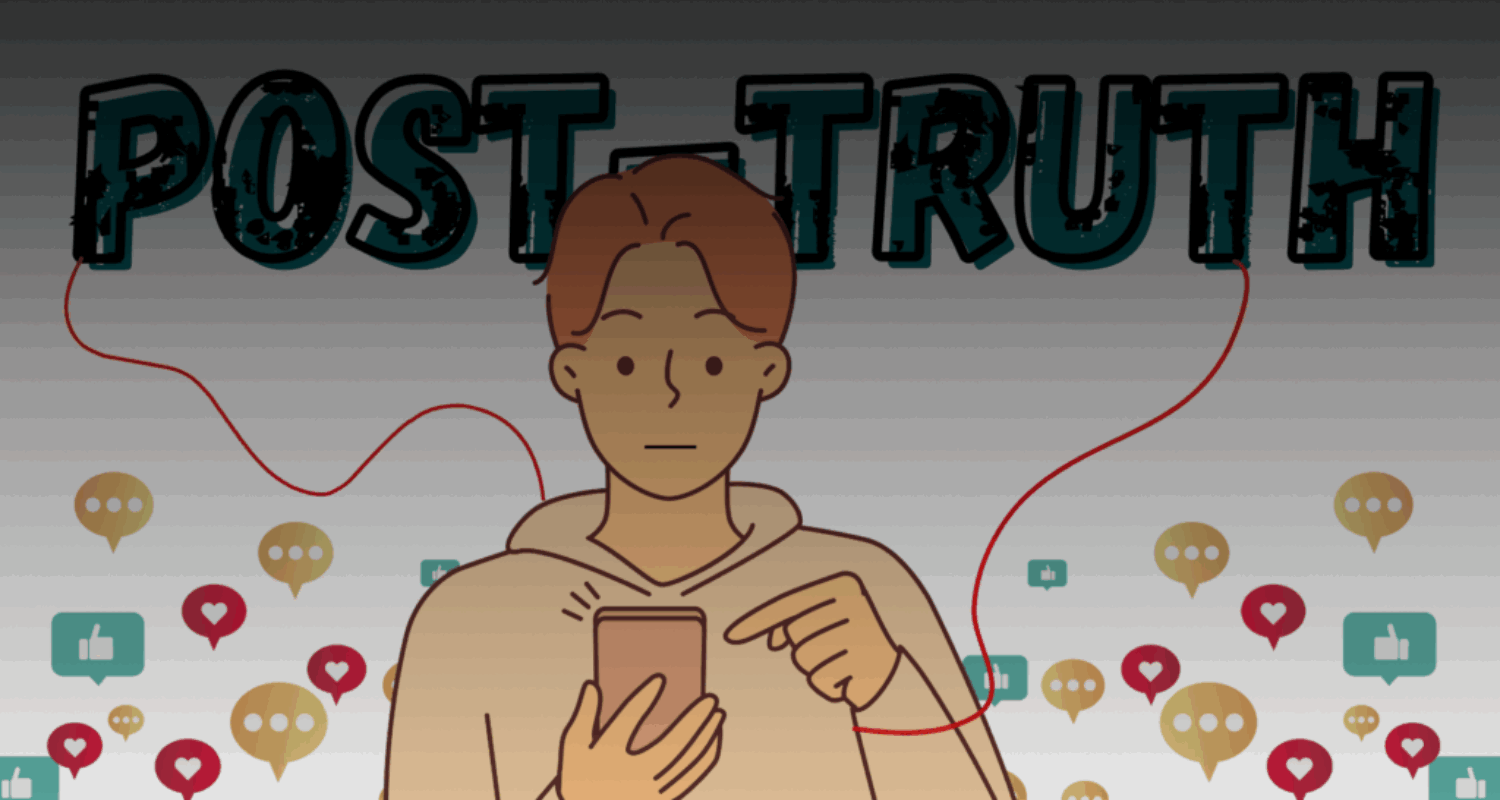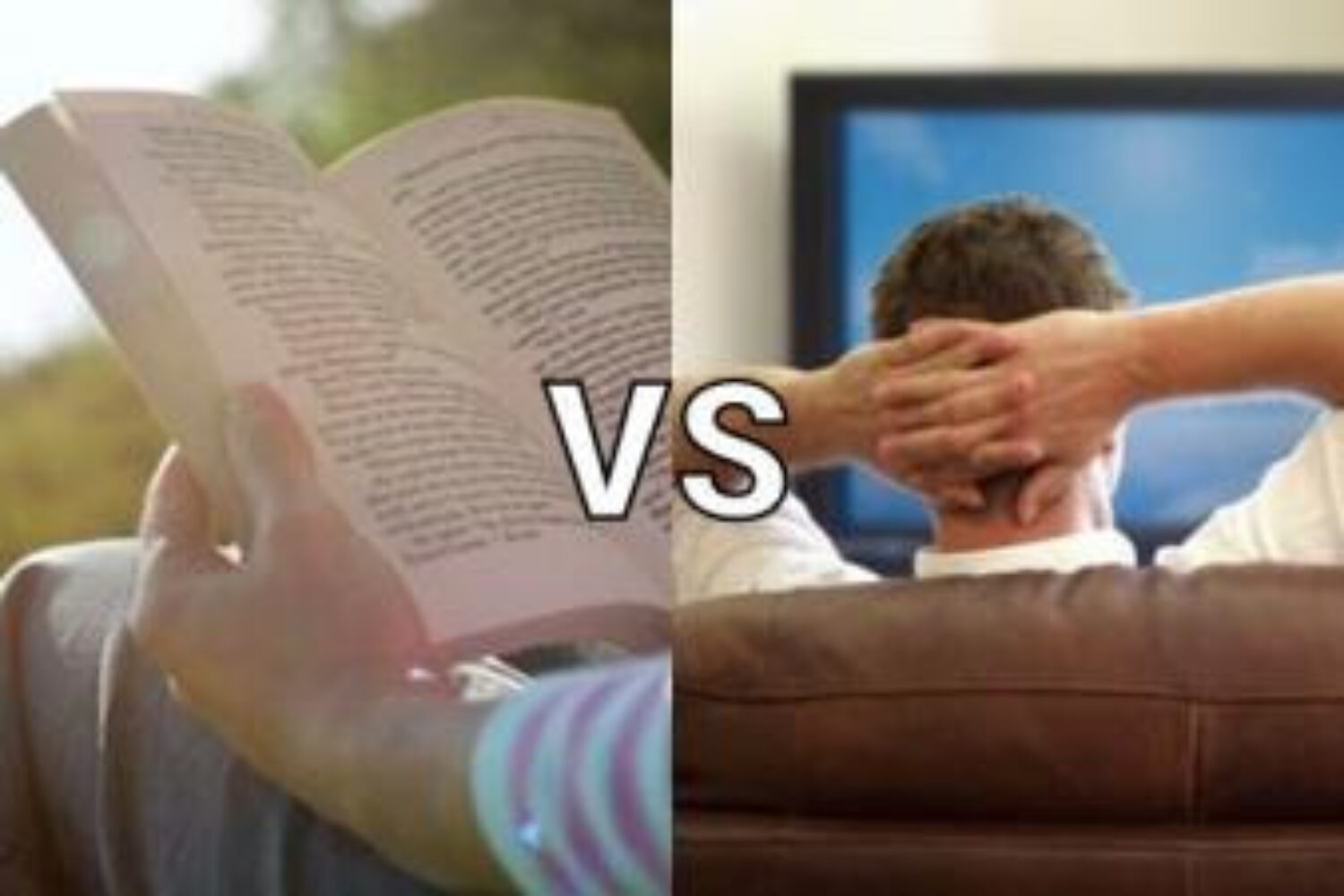Saat seseorang bersantai sambil menggeser layar ponsel, jari-jari meluncur tanpa henti, setiap geseran menghadirkan konten yang terasa begitu pas: meme yang menggemaskan, opini politik yang sejalan dengan pandangan, atau gaya hidup yang memicu keinginan untuk memiliki. Ada kepuasan instan, sensasi bahwa dunia digital ini memahami penggunanya sepenuhnya. Inilah wajah baru “kebenaran” yang kini dihuni – bukan lagi kebenaran yang ditempa melalui ujian rasional, melainkan yang dihasilkan oleh mesin algoritmik yang haus akan perhatian.
Dalam ranah pengetahuan tradisional, epistemologi menawarkan tiang-tiang penyangga kebenaran yang kokoh:
1 Korespondensi: Kebenaran dianggap sebagai cermin kenyataan. Sebuah pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan fakta objektif di dunia nyata. Misalnya, ketika hujan turun di luar jendela, pernyataan “Sekarang sedang hujan” dianggap benar karena berkorespondensi dengan realitas.
2 Koherensi: Kebenaran dipandang sebagai jaring logis yang rapi. Sebuah ide dianggap benar jika selaras dan tidak bertentangan dengan sistem pengetahuan lain yang telah diterima. Teori gravitasi Einstein, misalnya, dianggap benar bukan hanya karena pengamatan, tetapi juga karena koheren dengan kerangka fisika modern yang lebih luas.
3 Kegunaan (Pragmatisme): Kebenaran diukur dari fungsinya. Sebuah keyakinan dianggap benar jika membawa manfaat praktis, memecahkan masalah, atau membantu adaptasi. Keyakinan bahwa “menanam padi di musim hujan meningkatkan panen” dianggap benar karena terbukti berguna dan menghasilkan.
Ketiga tolok ukur ini berakar pada upaya manusia untuk memahami dunia secara rasional, kritis, dan objektif – sejauh yang memungkinkan. Proses ini menuntut verifikasi, analisis, dan sering kali, keraguan yang sehat. Namun, era imagologi kini telah mengemuka – sebuah istilah yang merujuk pada kekuatan citra, narasi, dan persepsi yang dibentuk secara masif dalam ekosistem digital.
Di panggung media sosial dan platform digital yang mendominasi percakapan modern, tolok ukur kebenaran mengalami perubahan mendasar. Penguasa di sini bukan lagi akal budi atau realitas objektif, melainkan algoritma yang cerdas namun berpihak.
Algoritma ini dirancang dengan tujuan utama untuk memaksimalkan keterlibatan (engagement). Algoritma berfungsi sebagai mesin presisi yang mempelajari pola perilaku digital – apa yang membuat seseorang berhenti menggeser layar, apa yang memicu like, komentar, share, atau waktu tonton yang lebih lama.
Dalam proses ini, logika kebenaran mengalami pergeseran:
1. Kebenaran sebagai Validasi: Algoritma mengenali bahwa keterlibatan paling tinggi terjadi ketika konten memvalidasi keyakinan, bias, dan identitas yang sudah ada. Alih-alih menyajikan kebenaran yang menantang pemikiran, algoritma lebih memilih konfirmasi yang menenangkan.
Jika seseorang mempercayai pandangan X, algoritma akan terus menghadirkan lebih banyak konten tentang X – bahkan kadang memperlihatkan karikatur ekstrem dari pandangan lawan, Y – sehingga memperkuat keyakinan bahwa X adalah satu-satunya kebenaran. Kebenaran diukur dari seberapa dalam konten menyentuh ego dan identitas pengguna.
2. Kebenaran sebagai Kepuasan Instan: Algoritma juga memahami bahwa manusia menyukai konten yang memanjakan. Konten yang menghibur, memicu kemarahan cepat, membangkitkan nostalgia, atau menawarkan solusi instan tanpa kompleksitas menjadi magnet perhatian.
Dalam logika algoritma, kebenaran diukur dari kemampuannya memberikan dorongan dopamin digital, menciptakan sensasi kepuasan dan kesenangan seketika, terlepas dari kedalaman, keakuratan, atau konsekuensi jangka panjangnya.
Akibatnya, terjadi amplifikasi masif. Algoritma tidak bersikap netral; ia secara aktif memperkuat segala sesuatu yang memenuhi dua kriteria ini – validasi dan kepuasan.
Suara-suara pinggiran yang ekstrem, teori konspirasi yang memuaskan rasa ingin tahu instan, informasi setengah benar yang menggugah emosi, hingga konten bohong (hoax) yang dirancang untuk memprovokasi keterlibatan – semua mendapat panggung besar selama mampu “beresonansi” dengan pola keterlibatan audiens tertentu.
Kebenaran objektif (korespondensi), konsistensi logis (koherensi), atau manfaat jangka panjang (kegunaan) sering kali kalah bersaing dengan kebenaran yang terasa enak dan menguatkan prasangka.
Inilah paradoks imagologi digital: manusia merasa lebih “terhubung” dan “terinformasi” dibandingkan sebelumnya, namun sebenarnya terjebak dalam “kebun berpagar” algoritmik – ruang gema (echo chamber) yang dindingnya dibangun dari preferensi pribadi yang terus diperkuat. Tolok ukur kebenaran bergeser dari pencarian objektif menuju penguatan subjektif, dari ujian rasional menuju kepuasan emosional instan.
Epistemologi mengajarkan pentingnya mengejar kebenaran meskipun pahit. Sebaliknya, imagologi algoritmik menawarkan kebenaran yang manis, nyaman, dan sesuai selera – sebuah fantasi yang dikurasi secara digital.
Dalam konteks ini, pertanyaan kritis yang perlu diajukan bukan hanya “Apakah ini benar?” dalam pengertian klasik, melainkan “Mengapa algoritma membuat seseorang mempercayai bahwa ini benar? Kebenaran seperti apa yang sedang dipanen dari keterlibatan digital?” Di era ini, kesadaran akan mekanisme di balik kurasi kebenaran digital menjadi keterampilan esensial untuk bertahan dalam lautan informasi.